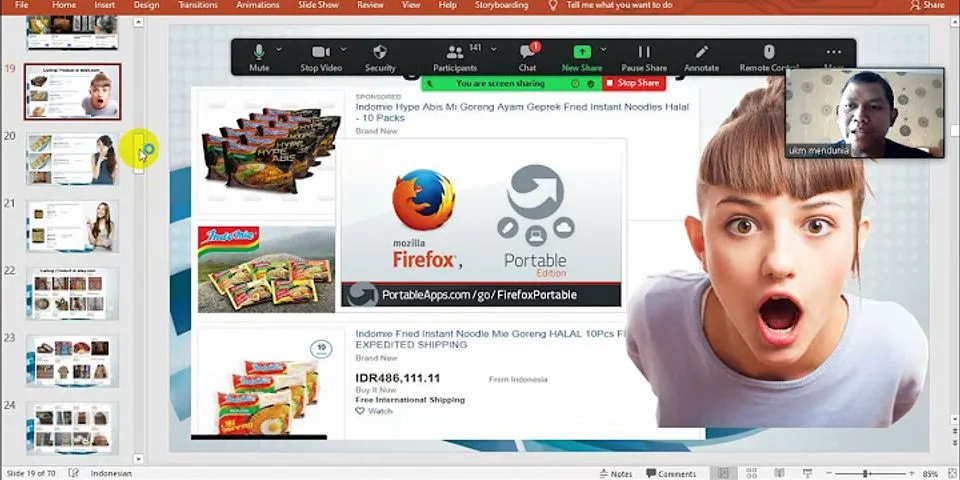Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim paling banyak di dunia. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang banyak dan persentase penduduk yang beragama Islam pun tinggi. Kondisi ini yang kemudian berpeluang terjadinya banyak pemahaman terhadap praktik keagamaan di Indonesia. Kelompok tertentu dipandang mampu untuk memahami hukum yang dibebankan kepadanya yang bersumber dari Alquran dan Hadits. Terlepas dari bagaimana mereka mendapatkan pemahaman itu, baik secara langsung mengkaji dua sumber itu atau melalui imam-imam madzhab tertentu yang sudah terakui keilmuannya. Namun di sisi lain ada sekelompok masyarakat yang tidak berpedoman terhadap dalil yang jelas ketika mengamalkan sesuatu. Mereka cukup mendengar dari orang yang mereka anggap mumpuni di bidang hukum (sebut saja Kiayi) mengenai hukum tertentu yang kemudian diamalkan tanpa memikirkan dari mana sang mufti (pemberi fatwa) tadi memperolehnya. Dan yang lebih ironis lagi adalah mereka yang jauh dari nilai-nilai agama dalam perilakunya walaupun notabene mereka Islam. Hal ini mungkin karena mereka buta akan Islam atau ada faktor lainnya. Menanggapi hal itu dirasa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan pentingnya menjalankan ajaran agama secara keseluruhan dan penuh dengan kesadaran. Semua itu dilakukan demi sebuah pengabdian dan rasa syukur manusia akan karunia tuhannya. Dan untuk mengetahui hukum-hukum dan kewajiban yang dibebankan kepadanya (mukallaf) manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu diharapkan mampu memahami perintah dan larangan yang harus dilaksanakan dan dijauhi serta termotivasi untuk memraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah letak urgensi thalab al-‘ilmi (menuntut ilmu) bagi seorang muslim demi mempertahankan eksistensinya sebagai orang yang taat beragama dan peduli terhadap dirinya. Karena mengetahui kewajiban hingga pada akhirnya ia wajib menjalankannya adalah kewajiban bagi setiap mukallaf. Dalam praktiknya, taqlid buta (mengikuti pendapat seseorang tanpa usaha untuk mengetahui dalilnya) masih sangat berpotensi di Indonesia. Alasannya adalah, yang pertama, mengikuti fatwa dari mufti itu lebih mudah dan praktis dibanding harus menggali hukum secara lansung yang dirasa berat dan menyita banyak waktu. Sehingga mayoritas umat Islam di Indonesia memilih taqlid pada salah satu pendapat tertentu daripada harus berijtihad. Alasan yang kedua, kecakapan untuk mengistinbathkan hukum dari sumbernya itu merupakan sesuatu yang tidak mudah dan memang orang-orang tertentu saja yang sanggup melaksanakannya. Dan justru jika semua orang dipaksakan untuk berijtihad akan dikawatirkan hasil dari ijtihadnya jauh dari nilai kebenaran dan cenderung asal-asalan. Taqlid mungkin masih mempunyai nilai positif namun yang dikhawatirkan adalah mencampurkan beberapa pendapat ulama’ dalam suatu permasalahan yang berimplikasi ketidakabsahan amal itu menurut pandangan masing-masing ulama’. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan pembahasan seputar Taqlid dan Talfiq dan aplikasinya dalam masyarakat. Taqlid dan Talfiq Sedangkan Talfiq adalah cara mengamalkan suatu ajaran agama dengan mengikuti secara taqlid tata cara berbagai madzhab, sehingga dalam satu amalan terdapat pendapat berbagai madzhab. Ulama’ Ushul Fiqh mendefinisakan Talfiq dengan melakukan suatu amalan dengan tata cara yang sama sekali tidak dikemukakan oleh mujtahid manapun (Insiklopedi Hukum Islam, 2001). Dalam masalah ini disyaratkan dua hal yaitu mengikuti pendapat dengan cara taklid dan adanya penggabungan beberapa pendapat dalam satu permasalahan. Dan terkait dengan permaslahan talfiq ini, ulama fiqh juga membahas persoalan mengambil amalan atau pendapat dari berbagai madzhab yang paling mudah dan ringan. Dalam istilah seperti ini disebut dengan tabarru’ur rukhash. Dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama’ berkenaan dengan hal ini Contoh talfiq yaitu dapat dikemukakan sebagai berikut. Ketika berwudhu khususnya saat menyapu kepala, seorang mengikuti tata cara yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi’i. Beliau berpandapat bahwa dalam berwudhu seorang cukup menyapu sebagian kepala, yang batas minimalnya tiga helai rambut. Setelah berwudhu orang tersebut bersentuhan kulit dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Sedangkan menurut Syafi’i persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan ajnaby (perempuan yang halal dinikahi) tanpa hijab membatalkan wudhu. Namun dalam persentuhan kulit setelah berwudhu orang tersebut mengambil pendapat Imam Abu Hanifah dan meninggalkan pendapat Syafi’i. Abu Hanifah menyatakan bahwa persentuhan kulit tersebut tidak membatalkan wudhu. Dalam kasus ini, pada amalan wudhu terkumpul dua pendapat sekaligus yaitu pendapat Imam asy-Syafi’i dan pendapat Imam Abu Hanifah. Dampaknya adalah amalan itu tidak dinilai benar (sah) oleh masing-masing imam alias batal. Pendapat 4 Imam Madzhab Mengenai Taklid Dari pernyataan 4 Imam madzhad di atas bahwa sebenarnya mereka pun menginginkan umat ini untuk meneliti pendapat yang mereka fatwakan dan berusaha menelusuri dalil yang dijadikan pegangan oleh mereka. Artinya tidak serta merta menerima pendapat mereka tanpa usaha untuk mengkritisi pendapat itu. Di sini letak kelemahan umat islam yang terkadang fanatik pada salah satu madzhab tanpa dibarengi dengan usaha untuk meneliti pendapat madzhabnya. Walaupan dari segi keilmuan dan kemampuan mengistinbatkan hukum mereka jauh lebih layak dibanding manusia pada umumnya. Akan lebih baik dan bijak jika kita tetap melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang muncul dengan tidak menafikan pendapat (ijtihad) mereka. Penutup 1. Taqlid adalah mengikuti pendapat salah seorang mujtahid tanpa mengetahuhi dalil yang dijadikan pegangan oleh mujtahid tersebut. 2. Talfiq adalah mengambil pandapat dari berbagai madzhab kemudian memilih yang paling mudah dan ringan dalam penerapannya (aplikasinya). 3. Taqlid dibolehkan dalam hukum-hukum yang memerlukan penelitian dan ijtihad sedangkan dalam hukum-hukum yang tidak memerlukan penelitian dan ijtihad (al-ma’lum min ad-din bi adh-dharurah) tidak diperbolekan taqlid secara mutlak. 4. Pada hakikatnya para Imam madzhab tidak mengaruskan kaum muslimin untuk taqlid pada pendapat mereka namun justru menyarankan untuk meneliti dalil secara individu. Saran Samsul Zakaria,
 Oleh: Hilmi Abedillah* Dahulu, para sahabat meminta fatwa hukum langsung kepada Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya. Setelah wafat, Nabi meninggalkan warisan berupa manuskrip Al Quran juga yang berada di dalam hafalan para sahabat. Baru pada abad ke-3 H dibukukanlah hadis yang sebelumnya hanya berada pada ingatan. Dengan begitu, sumber hukum Islam dapat digali dengan mudah. Pada masa tabiin dan tabiit tabiin, muncul banyak mujtahid yang menguasai Al Quran maupun hadis, selain juga ilmu-ilmu penunjang ijtihad. Mereka tidak terhitung jumlahnya, namun hanya beberapa yang diakui, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali. Sedangkan para awam yang tidak mampu melakukan ijtihad disebut dengan muqallid (orang yang taklid). Karena tidak bisa berijtihad sendiri, mereka mengikuti pendapat mujtahid yang sudah ada. Perbedaan keempat madzhab tersebut terasa mendasar, karena memiliki prinsip hukum yang berbeda-beda. Akibatnya, pendapat mereka tentang suatu masalah juga berbeda-beda. Dari hukum suatu ibadah, sampai syarat, rukun, dan kaifiyah (tatacara)-nya. Sementara muqallid dalam satu kondisi tidak bisa mengikuti madzhab secara utuh dan harus melakukan talfiq. Lazimnya, talfiq dalam fikih dan ushul fikih digunakan sebagai istilah: Majalah Tebuireng الإتيانُ في مسألةٍ واحدةٍ بكيفيةٍ لا تُوافقُ قولَ أحدٍ من المجتهدين السابقين “Menjalankan suatu masalah dengan cara yang tidak sesuai dengan satu pun mujtahid terdahulu.” Dengan begitu, talfiq menggabungkan dua/lebih pendapat madzhab berbeda dalam satu ibadah. Contohnya orang yang membasuh beberapa helai rambut ketika wudlu, mengikuti madzhab Syafi’i, dan ketika menyentuh wanita ia tidak mengulangi wudlunya lagi, mengikuti madzhab Abu Hanifah. Kemudian ia shalat. Shalat tersebut batal menurut Abu Hanifah, karena madzhabnya mengharuskan membasuh minimal seperempat kepala, selain juga batal menurut madzhab Syafi’i yang menganggap bahwa bersentuhan wanita membatalkan wudlu. Terkadang, talfiq dipakai sebagai istilah yang lebih umum menurut sebagian ulama. Yakni, muqallid menggunakan suatu madzhab untuk sebuah kasus, dan madzhab lain untuk kasus lain, sementara kedua kasus itu masih saling berhubungan. Jelas-jelas ini bukan suatu larangan, kecuali bagi pendapat yang mengharuskan berpegang teguh pada satu madzhab saja. Pandangan tentang keharusan berpegang pada satu madzhab saja dinilai rusak, karena menunjukkan sikap taklid yang melampaui batas. Pada zaman sahabat dan tabiin, muqallid dibebaskan untuk bertanya kepada siapa saja di kalangan ulama. Saat ia bertanya suatu masalah kepada seorang ulama, ia tidak dilarang bertanya pada ulama lain tentang kasus lain. Talfiq juga digunakan untuk menunjukkan pendapat baru (qaul jadid) yang terdiri dari dua pendapat berbeda dalam satu masalah, atau dengan sederhana bisa disebut “pembaruan pendapat baru”. Selain itu, juga dipakai sebagai fatwa mujtahid yang terdiri dari dua pendapat tanpa ada pengunggulan (tarjih) di antara keduanya. Ini dikarenakan mufti ingin mengeluarkan mustafti (orang yang meminta fatwa) dari posisi sulitnya. Inilah yang disebut dengan muro’atul khilaf. Ulama berbeda pendapat tentang talfiq yang dalam definisi pertama “menjalankan suatu masalah dengan cara yang tidak sesuai dengan satu pun mujtahid terdahulu”. Terkadang, muqallid melakukannya dengan sengaja, kadang juga tidak. Apabila hal itu dilakukan tanpa sengaja, maka jelas tidak dilarang. Karena ijma’ bahwa ia boleh mengamalkan fatwa dari mujtahid siapapun. Ia tidak dicegah meminta fatwa kepada Syafi’iyyah tentang wudlu dan meminta fatwa kepada Malikiyah tentang batalnya wudlu. Kemudian ia wudlu tanpa membasuh keseluruhan kepala dan menyentuh wanita lain. Apabila talfiq dilakukan sengaja, maka tidak sah. Karena bisa jadi ia jatuh dalam perbedaan nash-nash syariat yang ia tidak ketahui. Dan karena menjalankan pendapat baru tanpa ada fatwa merupakan tindakan yang didasari hawa nafsu. Itu bertentangan dengan prinsip beragama. Sebagian ulama memberikan syarat penting dalam talfiq: [1] tidak bertentangan dengan ijma’ atau nash Al Quran dan sunnah, [2] tidak digunakan untuk membebaskan diri dari tanggungan beban (tidak untuk meringankan). Namun, menurut madzhab Maliki, boleh taklid kepada setiap madzhab Islam yang mu’tamad (diakui), sekalipun talfiq, dalam keadaan darurat, hajat, lemah, maupun udzur. Karena talfiq tidak dilarang menurut Malikiyah, pun sebagian Hanafiyah, sebagaimana kebolehan mengambil pendapat paling ringan dari beberapa madzhab. Akan tetapi, talfiq harus didasari kebutuhan dan maslahat, bukan main-main atau mengikuti hawa nafsu. Karena agama Allah agama yang mudah, kebolehan talfiq merupakan bagian dari kemudahan itu. Allah berfirman, “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. al-Baqarah: 185). Sumber: Ushul Fiqh ‘Iyadl bin Nami, 333-334 Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu, I, 9 *Tim Redaksi Majalah Tebuireng |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Periklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 berikutyang Inc.