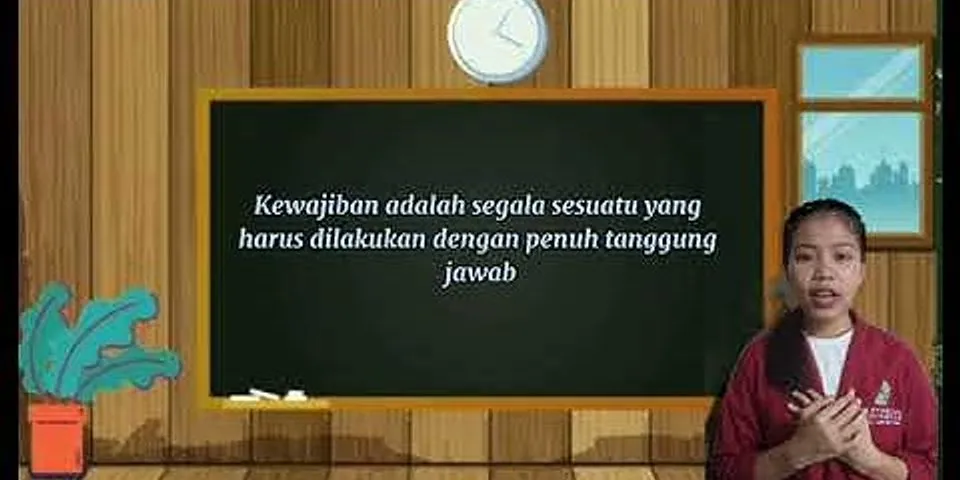Relasi patronase (patron-client relationship) yang terjadi pada masyarakat Sumedang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 berpengaruh terhadap terjadinya mobilitas sosial yang ditandai dengan meningkatnya jumlah golongan terpelajar yang berperan dalam lingkungannya. Kajian sejarah lokal yang dapat dijadikan salah satu sumber pelajaran sejarah di sekolah ini merupakan hasil penelitian di Museum Geusan Ulun Sumedang dan ditulis dengan menggunakan pendekatan sosio-antropologis. Kajian ini juga merekam struktur politik, relasi sosial antara golongan menak/priyayi dengan somah/cacah, kehidupan sosial-ekonomi, dan terjadinya mobilitas sosial untuk menggambarkan masyarakat Sumedang dalam berbagai dimensi pada kurun waktu tersebut. PengantarHubungan patronase (patron-client relationship) dan mobilitas sosial yang merupakan konsep-konsep relasi sosial yang dikaji dalam Sosiologi-Antropologi,[1] digunakan dalam kajian sejarah ini untuk melihat perkembangan yang terjadi pada masyarakat Sumedang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kajian ini berangkat dari realitas sejarah yang dikembangkan oleh R.M. Abdullah Kartadibrata (1989) dalam bukunya mengenai salah seorang bupati Sumedang yang digambarkannya sebagai berikut: Tanggal 25 April 1921 diresmikan berdirinya Lingga Monumen Peringatan Bupati Sumedang, Pangeran Aria Soeria Atmadja, yang terletak di tengah-tengah alun-alun Sumedang. Peresmian tersebut dilakukan dengan upacara yang sangat meriah. Di sekitar pendopo kabupaten dihias dengan umbul-umbul beraneka warna untuk menyambut kedatangan para undangan yaitu para bupati di Priangan seperti bupati Sumedang sendiri, Ciamis, Tasikmalaya, Bandung, Cianjur, dan Sukabumi serta para pembesar Belanda dari Batavia dan Bandung seperti Gubernur Jenderal De Fock, Residen dan Asisten Residen serta beberapa pejabat pemerintah Hindia Belanda lainnya. Mereka semua berkumpul di Srimanganti bersama para menak/priyayi Sumedang untuk tujuan yang sama yaitu mengenang jasa bupati Soeria Atmadja melalui monumen yang diresmikan saat itu. Kemeriahan peresmian tersebut terasa dengan berkumpulnya ribuan masyarakat Sumedang di sekitar alun-alun yang datang dari pelosok Sumedang.[2] Berdasarkan kutipan di atas, timbul pertanyaan sebagai berikut. Pertama, mengapa pemerintah kolonial Belanda memberikan penghargaan – berupa pembangunan monumen dan hadiah Payung Songsong Kuning dan Songsong Djene – kepada seorang bupati? Kedua, bagaimanakah hubungan antara bupati Sumedang dengan rakyatnya? Dan ketiga, apakah pola hubungan patronase di Sumedang berpengaruh terhadap terjadinya mobilitas sosial warganya? Dengan kajian terhadap berbagai sumber, tulisan ini berusaha untuk menjelaskan gejala patronase dan mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat Sumedang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Struktur Politik PemerintahanHubungan patronase antara elite Sumedang dengan bawahannya dan terjadinya perubahan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial-politik pemerintahannya. Struktur politik pemerintahan kabupaten Sumedang pada zaman kolonial Belanda adalah sama dengan struktur politik di kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa. Namun demikian, berbeda dengan bupati-bupati di Jawa pada masa kolonial, para bupati Sumedang sebagai elite politik adalah merupakan golongan aristokrat kerajaan Sumedang Larang. Menurut sumber sejarah lisan,[3] kerajaan ini didirikan pada tahun 900-an oleh Prabu Taji Malela yang merupakan keturunan Sumedang asli. Dalam garis genealogis, mereka selalu merujuk pada leluhur Sumedang Larang, terutama Pangeran Geusan Ulun yang ber-ibu dari keturunan Pajajaran serta ber-ayah dari keturunan Cirebon yang beragama Islam, yang memerintah antara tahun 1580-1608.[4] Sebelum jatuh ke tangan VOC, kerajaan Sumedang Larang ini pernah dikuasai oleh Mataram di bawah bupati Pangeran Rangga Gempol I (1620-1625), Dipati Ukur (1625-1629), Rangga Gempol II (1641-1656), dan bupati Sumedang asli yaitu Pangeran Kusumahdinata V (1656-1706). Pengaruh Mataram dalam kehidupan aristokrasi Sumedang pada masa bupati-bupati selanjutnya juga cukup besar.[5] Pada masa pemerintahan Mataram, VOC, dan Hindia Belanda, status bupati-bupati Sumedang tetap berada dalam puncak hirarki kekuasaan di daerahnya, diikuti oleh para pejabat kebupaten yang kepangkatannya hampir sama dengan tradisi aristokrasi Jawa, seperti dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo,[6] yaitu berdasarkan ikatan darah dengan bupati (blood-relationship with the ruler) atau berdasarkan bakat serta kecakapan yang dimiliki oleh orang yang akan diangkat itu. Mereka kemudian menempati jabatan-jabatan birokrasi di lingkungan kabupaten. Mereka termasuk ke dalam the rulling class, elite atau patron terhadap massa rakyat yang disebut cacah yang jumlahnya lebih banyak. Dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda, para bupati Sumedang juga telah berperan sebagai mediator, middleman atau penghubung, antara sistem sosio-ekonomi dan budaya lokal dengan sistem pemerintahan kolonial yang modern.[7] Gelar-gelar kebangsawanan dan gelar karena jabatan seperti Pangeran, Tumenggung, Adipati dan Aria – yang merupakan gelar aristokrasi Mataram – tetap dipertahankan ketika para bupati Sumedang dijadikan pegawai pemerintah kolonial. Para masa pemerintahan kolonial Belanda tersebut, yakni sepanjang abad ke-19, jabatan-jabatan sipil pemerintah kolonial yang dipegang oleh golongan pribumi selalu dikaitkan dengan status kebangsawanan atau aristokrasi.[8] Pemberian gelar kepada pihak bupati itu dianggap sebagai adanya pengakuan status “elite” yang menduduki hirarki kekuasaan di daerahnya. Sedangkan bagi penguasa Belanda sendiri hal itu untuk mempermudah dalam melaksanakan pemerintahannya yang bersifat indirect rule terhadap rakyat Sumedang yang jumlahnya ratusan ribu,[9] yang sulit dikontrol oleh pemerintahan kolonial Belanda apabila dilakukan secara langsung. Para bupati Sumedang pada abad ke-19, sebagai penguasa pribumi atau the native rulers[10] — walaupun berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah kolonial – tetap menampilkan karakter yang berbeda dengan bupati-bupati lain di Jawa. Sebagai elite keturunan raja-raja Sumedang Larang, mereka memiliki “darah biru” keluarga aristokrat, menak atau bangsawan, yang di dalam konsep-konsep tradisional harus memiliki mental, moral, dan rasional yang tinggi serta lebih penting lagi harus berorientasi ke bawah, kepada rakyat yang menjadi bawahannya.[11] Dengan demikian, karena karakter yang bebeda itulah mereka tetap berorientasi ke bawah dengan cara memperhatikan nasib rakyatnya melalui beberapa tindakan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dalam uraian berikut akan ditunjukkan bagaimana sikap bupati Sumedang yang berani menentang pemerintah kolonial Belanda yang dinilainya merugikan kepentingan rakyat. Kehidupan Sosial-EkonomiHubungan patronase antara golongan elite Sumedang dengan cacah terlihat pula dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya. Kehidupan ekonomi yang menonjol adalah sektor agraria dengan pusat pertumbuhan di pendopo kabupaten. Kota kabupaten Sumedang mulai berkembang pesat sebagai salah satu kota kabupaten di Jawa Barat setelah dibukanya jalan raya pos oleh Daendels. Namun demikian, pertumbuh kota ini sebenarnya telah terjadi sejak Taji Malela membuka wilayah Sumedang untuk pusat pemerintahan pada abad ke-10 yang diperkirakan di sekitar pendopo kabupaten sekarang. Sejak itu, kota Sumedang telah berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan sektor agraria, dan tempat pemukiman keluarga bupati, para menak/priyayi yang bekerja di lingkungan pendopo kabupaten. Peran tersebut telah lama dimiliki oleh kota Sumedang, bahkan mendahului kota Bandung yang pada akhir abad ke-18 masih belum menunjukkan tanda-tanda sebuah kota. Kondisi geografis Sumedang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kota Sumedang. Wilayah Sumedang terdiri dari pegunungan dan perbukitan. Tofografi tanahnya yang berada pada dataran tinggi yang miring menyulitkan dikembangkannya lahan persawahan yang datar dan luas. Tanahnya terdiri dari cadas-pasir yang kurang subur untuk pertanian. Sungai yang mengalir di wilayah Sumedang, yakni Cimanuk, tidak membantu kesuburan tanah di sekitarnya karena tanah-tanah tersebut berada terlalu tinggi di atas sungai. Karena kemiringan itulah maka air yang mengalir sulit dimanfaatkan untuk kepentingan pengairan sawah. Dengan keadaan tanah yang kurang subur tersebut rakyat memanfaatkannya untuk kepentingan hidup sehari-hari. Sedangkan penduduk kota yang pada umumnya terdiri dari para menak/priyayi tidak terpengaruh oleh kegiatan ekonomi rakyat di pedesaan. Tanah pertanian yang sempit tersebut dimanfaatkan oleh penduduk desa untuk bertanam padi. Seperti penduduk pedesaan pada umumnya di Jawa Barat pada abad ke-19,[12] penduduk desa-desa di Sumedang juga membuka sawah. Sawah tersebut dimiliki secara perorangan dan secara tanah komunal. Sebagian tanah lainnya adalah tanah lungguh yang diperuntukkan bagi para pamong praja desa serta para menak yang menguasai daerah tertentu. Karena tanahnya yang miring dan terletak di perbukitan itu maka penduduk desa menggarapnya dengan cara subsisten, meminjam istilah Clifford Geertz,[13] sehingga hasilnya pun hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari selain untuk membayar kewajiban-kewajiban tertentu seperti upeti atau somah kepada para menak. Bisa dikatakan bahwa para petani Sumedang, dengan pola pertanian subsistensi tersebut, mengalami involusi pertanian karena tidak berhasil meningkatkan produksi untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik. Membuka lahan-lahan persawahan baru di daerah Sumedang bukan hanya inisiatif penduduk desa setempat tetapi juga karena dorongan penguasa Mataram, Sultan Agung, terutama setelah Sumedang berada di bawah pengaruhnya yang diserahkan kepada pemerintahan bupati Pangeran Kusumahdinata atau lebih dikenal dengan Pangeran Gempol.[14] Dibawah pengaruh Mataram, wilayah Sumedang yang semula mencakup Priangan Timur dipersempit hanya meliputi Sumedang sekarang ditambah dengan Garut dan Limbangan, sejalan dengan didirikannya kabupaten lainnya seperti Bandung, Parakanmuncang, Sukapura, dan Galuh. Penduduk Sumedang mulai berkenalan dengan tanaman “modern” setelah kabupaten Sumedang diserahkan oleh Mataram (dibawah Amangkurat II melalui Traktat Tahun 1677) kepada VOC. Sejak saat itu bupati Sumedang harus berperan sebagai client yang mejalankan kebijaksanaan patron-nya yakni VOC. Dengan kebijaksanaan ekonomi VOC, penduduk Sumedang harus mengikuti sistem penyerahan hasil tanaman yang dikenal sebagai Sistem Priangan atau Preangerstelsel berupa tanaman kopi. Di bawah sistem ekonomi tersebut, penduduk Sumedang yang semula hanya mengenal tanaman padi, harus menanam kopi yang selanjutnya harus diserahkan kepada bupati mereka untuk memenuhi target penyerahan ke VOC, yakni sejumlah 20.000 pikul per tahun.[15] Dengan demikian, para petani Sumedang yang secara tradisional menanam padi dalam pola subsisten itu telah memperoleh beban baru berupa tanaman wajib untuk memenuhi perintah bupati mereka sebagai kepanjangan tangan dari VOC. Dibukanya Jalan Raya Pos pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) yang menghubungkan Batavia-Cianjur-Bandung sampai Sumedang tidak berpengaruh positif terhadap kehidupan ekonomi rakyat Sumedang, terutama yang hidup di pedesaan. Sebaliknya, dibukanya jalur komunikasi dan transportasi tersebut semakin mengintensifkan pengaruh penguasa kolonial, baik Inggris maupun Hindia Belanda terhadap feodalisme di kalangan menak Sumedang. Kehidupan ekonomi rakyat masih tetap bertani dengan memakai pola subsistensi, selain ditambah beban baru berupa penyerahan Preangerstelsel yang terus diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Jawa Barat, termasuk di Sumedang, sampai berakhirnya Sistem Taman Paksa (Cultuurstelsel) pada tahun 1870. Semakin lancarnya komunikasi antara pusat pemerintahan di Batavia dengan Sumedang, setelah dibukanya Jalan Raya Pos tersebut, tidak mengubah hirarki kekuasaan pemerintahan di Sumedang. Hirarki kekuasaan bupati masih tetap menggunakan pola kesultanan Mataram. Pangkat tertinggi bupati adalah Pangeran, kemudian Tumenggung yang membawahi tingkat penguasa di bawahnya seperti Mantri, Wedana, dan seterusnya sampai Lurah. Struktur ini tetap dipertahankan baik pada masa Daendels maupun pada masa pemerintah Hindia Belanda. Mereka juga mendapat gelar-gelar tertentu sesuai dengan prestasi dan tingkat pengabdian kepada pemerintah kolonial seperti Demang, Tumenggung, Aria, Adipati, dan Dalem. Pada abad ke-19 kita mengenal bupati Pangeran Kornel, Dalem Adipati Kusumahyuda (Dalem Ageung), Dalem Adipati Kusumahdinata (Dalem Alit), Raden Tumenggung Suriadilaga, Pangeran Suriakusumah Adinata (Pangeran Sugih) dengan gelar Raden Tumenggung, dan Pangeran Aria Suria Atmaja (1883-1919) yang mendapat banyak gelar seperti Raden Rangga, Aria Pangeran, dan Adipati.[16] Sebagai “pegawai” yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda, para bupati Sumedang termasuk kepanjangan tangan pemerintah kolonial sejak zaman VOC, Daendels, Inggris, dan Hindia Belanda. Akan tetapi nampaknya, berbeda dengan bupati-bupati lainnya di Jawa yang sepenuhnya menjalankan kepentingan kolonial, terutama untuk meningkatkan produksi/hasil pertanian menurut sistem ekonomi yang diberlakukan pada waktu itu, para bupati Sumedang tidak sepenuhnya menjalankan aturan pemerintah kolonial apabila hal itu bertentangan atau merugikan kepentingan rakyatnya terutama rakyat golongan bawah. Misalnya Pangeran Kusumahdinata, yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Kornel, pernah menantang Gubernur Jenderal Daendels yang memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan pembangunan jalan melewati gunung yang penuh dengan cadas yang keras. Karena target yang diminta Daendels tidak bisa dipenuhinya, Pangeran Kornel pun siap berhadapan dengan Daendels yang memaksakan kehendaknya itu. Begitu juga dengan bupati Raden Tumenggung Suria Kusumah Adinata yang melihat aturan wajib penyerahan tanaman tarum (nila) terlalu membebankan rakyat, menentang aturan tersebut. Aturan tersebut kemudian dicabut pada tahun 1855 sehingga petani Sumedang bebas dari tanam wajib nila. Begitu juga dengan bupati Pangeran Aria Suria Atmaja yang menjalankan kebijaksanaannya lebih banyak mementingkan kepentingan rakyat daripada hanya mengabdi pada kepentingan kolonial.[17] Sebagai kepada daerah yang pengangkatannya “mendapat restu” dari pemerintah kolonial, para bupati Sumedang berperan sebagai client yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan ekonomi dan politik sang patron pemerintah Hindia Belanda. Hubungan patron-client tersebut harus berjalan dengan baik. Sang patron memberikan perlindungan, memberikan penghargaan dan gelar-gelar seperti Tumenggung, Aria, Adipati, dan sebagainya. Pemerintah kolonial juga tetap mempertahankan tradisi kehidupan keraton Mataram di pendopo kabupaten Sumedang, meskipun para bupatinya tetap berperan sebagai pegawai pemerintah kolonial yang bertugas menjalankan kebijaksanaannya di daerah dan sebagai perantara, middleman, antara penguasa kolonial dengan rakyatnya. Dengan berbagai gelar yang diberikannya, para bupati memiliki lambang-lambang kebesaran tertentu. Gaya hidupnya menunjukkan kebesaran-kebesaran tertentu seperti jumlah pengikutnya yang banyak, tingkat konsumsi yang tinggi, dan rumah tangga yang besar. Misalnya, bupati Pangeran Suria Kusumah Adinata (1836-1882) memiliki banyak isteri, sampai memiliki anak lebih dari 100 orang (?) dan cucu yang lebih banyak lagi. Karena kekayaannya yang melimpah dan konsumsinya yang berlebih itu maka diapun mendapat gelar Pangeran Sugih, pangeran yang makmur. Stratifikasi SosialSebagai penguasa tradisional, yang dilegitimasi oleh pemerintah kolonial Belanda, bupati Sumedang berada di puncak hirarki sosial. Sebagai pangeran di daerahnya, para bupati dibantu oleh pembantu-pembatunya yang biasanya berasal dari lingkungan keluarga yang disebut para priyayi atau para “adik raja”.[18] Yang berhak menduduki bupati adalah anak tertua, walaupun tidak tertutup kemungkinan anak kedua, ketiga, atau adiknya yang menggantikannya. Seperti pengganti Pangeran Aria Suria Atmaja yang wafat pada tahun 1919 adalah salah seorang anggota keluarga yang agak jauh dari keturunan pangeran. Penggantinya dipilih berdasarkan kesepakatan keluarga dan restu dari pemerintah kolonial Belanda. Kekayaan bupati diperoleh dari hasil pertanian yang langsung dimiliki dan dibawah kontrol keluarga bupati. Mereka juga memungut pajak dari rakyat atau somah yang memiliki kewajiban-kewajiban tradisional berupa persembahan kepada para menak/priyayi di kabupaten.[19] Akan tetapi sejak tahun 1871 (pada masa pemerintahan bupati Pangeran Sugih) hak-hak istimewa tradisional ini dihapuskan berdasarkan pertimbangan bahwa para bupati telah lama menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda yang memberinya gaji.[20] Meskipun hal ini menyebabkan berkurangnya hak-hak tradisional dan kewenangan bupati dalam menjalankan pemerintahan tradisionalnya. Ikatan tradisional antara bupati sebagai penguasa tradisional dengan para petani yang menggarap tanah-tanah pertanian yang mungkin dianggapnya milik sang pengeran, tumenggung atau adipati, menyebabkan saluran upeti dan persembahan dari somah tetap mengalir ke lingkungan menak kabupaten. Para bupati masih tetap memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan pemerintahannya. Misalnya Pangeran Sugih, meskipun tidak memiliki hak atas pemungutan pajak dari somah tetapi tetap memiliki kekayaan yang berlimpah. Sedangkan Pangeran Aria Suria Atmaja, meskipun berperan sebagai pegawai pemerintah kolonial, tetapi tetap mampu menjalankan pemerintahan dengan baik, malah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai kebijaksanannya di bidang ekonomi.[21] Dengan demikian, hubungan patron-client antar keluarga bupati dengan para petani penggarap sebagai rakyatnya bisa merupakan akomodasi terhadap pembatasan-pembatasan hak-hak tradisional keluarga bupati Sumedang oleh penguasa kolonial Belanda. Hubungan tersebut tetap memberikan keuntungan terhadap kedua belah pihak. Keluarga menak atau priyayi dari bupati akan tetap mendapat hak-hak tradisional di berbagai bidang, sedangkan para petani sebagai somah tetap mendapat perlindungan dan jaminan berupa pengerjaan tanah-tanah pertanian yang mungkin masih menjadi hak milik tradisional keluarga bupati. Seperti telah disinggung di atas, gaya hidup lingkungan menak atau priyayi kabupaten Sumedang masih meniru lingkungan keraton Mataram. Gelar Pangeran, Adipati, Tumenggung adalah gelar kesultanan Mataram yang statusnya berada dibawah Sultan Mataram yang diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda dan diterima dengan baik oleh para bupati, meskipun mereka tidak lagi berada di bawah Sultan Mataram melainkan di bawah kekuasaan para Residen Priangan. Para bupati bersama keluarganya tinggal di lingkungan kabupaten atau Srimanganti yang berlokasi di pusat kota kabupaten, yaitu di depan alun-alun sejajar dengan pendopo dan mesjid. Di lingkungan tersebut juga dibangun sarana rekreasi keluarga menak/priyayi seperti kolam pemancingan yang letaknya di belakang Pendopo. Bangunan pendopo dibangun dengan menggunakan kayu jati kelas satu yang didatangkan dari perkebunan jati di kabupaten Sumedang. Anggota keluarga menak/priyayi lainnya seperti jaksa, penghulu, atau pegawai lainnya yang dekat dengan simbol-simbol kekuasaan kabupaten tinggal di pemukiman sekitar alun-alun dan jalan yang membentang ke arah barat dari alun-alun menuju ke arah Bandung. Kawasan inilah yang merupakan cikal bakal kota Sumedang sekarang. Dapat dikatakan bahwa kota Sumedang merupakan kotanya para menak/priyayi. Di sebelah timur alun-alun terdapat pemukiman penduduk kota lainnya. Umumnya mereka terdiri dari para pedagang kecil yang berjualan di pasar yang lokasinya terletak di sepanjang Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Daendels. Mereka adalah penduduk kota yang statusnya berada di bawah para menak/priyayi. Para menak/priyayi yang bermukim di kawasan barat menyebut mereka sebagai “orang pasar” yaitu suatu sebutan untuk golongan bawah atau lebih rendah dari para menak/priyayi. Apabila mereka melewati alun-alun atau Srimanganti, mereka selalu berjalan sambil menunduk sebagai tanda hormat kepada Kangjeng Pangeran atau sebagai pengakuan bahwa status mereka berada dibawah para menak/priyayi. Sikap rakyat yang demikian menunjukkan betapa hormatnya mereka terhadap bupati dan keluarganya yang dianggap berjasa dalam memberikan perlindungan kepada mereka.[22] Stratifikasi sosial di Sumedang didasarkan atas garis genealogis, status pekerjaan, dan kemampuan masyarakat dalam mengejar simbol-simbol lingkungan ke-menak/priyayi-an, serta jauh-dekatnya mereka terhadap simbol kekuasaan Barat. Secara garis besar hanya ada dua lapisan masyarakat yaitu menak/priyayi dan bukan menak/priyayi. Golongan menak/priyayi terdiri atas keluarga bupati, para pembantu dekatnya yang juga memiliki pertalian dengan keluarga, para pekerja lingkungan pendopo seperti jaksa, penghulu, dan sebagainya. Pada lapisan kedua terdiri dari penduduk kota yang bukan menak/priyayi seperti pedagang kecil, serta para petani penggarap tanah milik menak/priyayi yang disebut panyawah atau pangebon. Hubungan di antara keduanya dapat digambarkan sebagai hubungan patron-client seperti digambarkan oleh Sartono Kartodirdjo.[23] Di mata penguasa kolonial, seperti Residen dan Asisten Residen, kedudukan para bupati berada di bawahnya walaupun mereka telah memiliki berbagai kebesaran dari pemerintah kolonial Belanda. Bagi para bupati, tentu saja, kedudukan ini sangat tidak mengenakkan. Karena itu, untuk meningkatkan status sosial dan memudahkan mobilitas, mereka perlu menggunakan lambang-lambang yang biasa dipergunakan oleh para penguasa Barat. Salah satu sarana yang dipakai adalah penggunaan bahasa Belanda. Ada semacam anggapan di lingkungan para bupati Sumedang bahwa dengan penguasaan bahasa Belanda maka status mereka bisa disejajarkan dengan penguasa kolonial dan akan menambah keberanian tersendiri dalam menghadapi penguasa kolonial. Sebagai contoh, Pangeran Kornel dengan bangga menggunakan bahasa Belanda untuk menentang pemaksaan Gubernur Jenderal Daendels terhadap target penyelesaian pembangunan jalan yang memotong gunung yang terletak di sebelah barat kota Sumedang.[24] Begitu juga dengan para bupati lainnya, berusaha menguasai bahasa tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga akan menambah kewibawaan dan status sosialnya. Berbagai cara dilakukan untuk bisa menguasai bahasa Belanda itu. Ada yang mendatangkan guru private atau dengan meningkatkan pergaulan dengan para pejabat kolonial Belanda. Misalnya yang dilakukan oleh Pangeran Aria Suria Atmaja. Dia senang sekali bergaul dengan berbagai kalangan elite Belanda mulai dari Residen Priangan, Asisten Residen, atau pengusaha perkebunan seperti Jung Hunh.[25] Dengan penguasaan bahasa Belanda yang baik itu, para bupati Sumedang menganggap status mereka bisa sejajar dengan para penguasa kolonial Belanda. Pada lapisan kedua, para petani yang hidup di luar lingkungan pendopo, juga memiliki dasar stratifikasi sosial tersendiri. Sama seperti para petani Priangan lainnya, status mereka didasarkan atas hubungannya dengan tanah serta lamanya tinggal di desa tersebut.[26] Pada lapisan pertama adalah para pemiliki sawah, kebun, atau rumah dengan pekarangan yang luas. Para cikal-bakal, yang banyak di antaranya menjadi kepala desa atau kuwu/lurah, termasuk ke dalam lapisan ini. Lapisan kedua adalah para penggarap tanah milik orang lain dan yang hanya memiliki tanah lebih kecil. Dan lapisan terakhir adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki tanah, fungsinya hanya sebagai penggarap, panyawah atau pangebon.[27] Para pemilik tanah bisa mengidentikkan dirinya sebagai menak/priyayi kecil yang hidup di lingkungan desa. Pengidentifikasian sebagai menak/priyayi itu akan semakin kuat setelah mereka diangkat sebagai lurah atau kuwu atau penghulu desa yang mendapat hak pengelolaan atas tanah lungguh atau tanah jabatan. Sebagai menak/priyayi tingkat desa, mereka memiliki kedudukan terhormat di mata penduduk desa lainnya, terlebih-lebih mereka juga berhak menyandang gelar seperti raden. Dengan demikian, di luar pusat pemerintahan, di desa terdapat golongan menak/priyayi yang di dalam stratifikasi sosial mereka bisa dimasukkan ke dalam lapisan pertama, meskipun hak-haknya lebih terbatas. Hubungan Patron-Client Hubungan patron-client para bupati dan keluarganya di Sumedang dengan para petani bawahannya cenderung bersifat timbal-balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai masyarakat yang mewarisi tradisi Mataram, nampaknya merekapun terpengaruh oleh konsep manungaling kawula-gusti. Manunggal antara hamba (makhluk) dengan Tuhan (Khalik) yang kemudian diartikan sebagai manunggal antara rakyat dengan penguasa.[28] Hubungan di antara mereka itu berupa pengabdian kawula atau hamba terhadap raja atau penguasa, dan perlindungan raja/penguasa terhadap hamba/kawula. Bagi masyarakat Sumedang yang hidup dalam alam agraris, pola pemilikan tanah, dan proses pengerjaan tanah menjadi ciri dari kehidupan feodal mereka. Proses pengabdian para petani sebagai kawula biasanya dilakukan melalui penyediaan jasa berupa produksi atau tenaga kerja sebagai imbalan atas perlindungan dan jaminan hidup penguasa agar mereka terus bisa memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Para petani memberikan caos berupa persembahan upeti kepada penguasa dari golongan menak/priyayi itu. Sebaliknya para menak/priyayi juga terus memberikan jaminan agar para client mereka tersebut tetap menjadi pengikut dan pengabdi yang setia. Di Sumedang, para pengikut dan pengabdi itu disebut somah yang memiliki kewajiban mengerjakan tanah milik golongan menak/priyayi. Semakin besar jumlah somah semakin besar pula jumlah pajak atau persembahan lainnya yang akan diperoleh oleh golongan menak/priyayi. Para menak/priyayi itu akan memperoleh keuntungan ekonomis berupa jasa dan produksi yang diberikan oleh somah. Tidak diketahui dengan pasti apakah menak/priyayi Sumedang itu menganggap jumlah somah lebih penting dari pada luas tanah, seperti persepsi para priyayi Jawa lainnya yang beranggapan bahwa jumlah cacah atau pengikut lebih penting dari pada luas tanah.[29] Bagi para priyayi Jawa, tanah tidak memiliki arti apa-apa karena mereka tidak mungkin bisa mengerjakan secara langsung, kecuali hanya menikmati persembahan yang diberikan oleh para petani. Dengan demikian, jumlah cacah-lah yang akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh para priyayi. Hubungan seperti ini pulalah yang dinikmati oleh para menak/priyayi Sumedang. Ketika Sumedang berada di bawah pemerintah kolonial Belanda, hubungan tersebut dilestarikan karena pemerintah kolonial melihat bahwa hal itu akan sangat menguntungkan mereka dalam menjalankan pemerintahan dan kebijaksanaan ekonominya. Pada saat itu memang hubungan tersebut lebih bersifat satu arah karena hanya ada tuntutan dan kewajiban para menak/priyayi, yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda, dari para petani. Mereka dibebani berbagai aturan dan beban seperti wajib tanam kopi menurut Preangerstelsel. Pada masa itu hanya golongan menak/priyayi-lah yang nampaknya lebih banyak diuntungkan oleh pola hubungan patron-client, terlebih-lebih apabila para bupati, sebagai wujud dari menak/priyayi paling tinggi, lebih berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda. Kencenderungan ke arah pola hubungan patron-client yang timbal-balik dan saling menguntukan antara para menak/priyayi dengan para somah itu sudah dirintis oleh Pangeran Kusumahdinata (Pangeran Kornel) yang berani menentang pemerintahan Daendels untuk membela rakyatnya dari beban yang terlalu berat untuk membangun jalan; atau oleh Pangeran Sugih yang menyatakan keberatan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan “tanam nila” kepada para petani di Sumedang.[30] Tindakan positif para bupati tersebut diteruskan oleh Pangeran Aria Suria Atmaja yang memerintah sebagai bupati Sumedang dari tahun 1883-1919. Pada masa bupati inilah hubungan antara kedua strata masyarakat tersebut saling menguntungkan. Beberapa kebijaksanaan bupati di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, dirasakan manfaatnya oleh rakyat Sumedang.[31] Pandangan Pangeran Aria Suria Atmaja yang jauh ke depan, perhatiannya yang besar terhadap kemajuan para petani, somah, dan para menak/priyayi itu menyebabkan banyak kemajuan di berbagai bidang. Pembangunan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan bukan semata-mata memperluas daerah persawahan dengan membuka lahan-lahan baru, mendatangkan ternak bibit unggul dari daerah lain, dan membuka kawasan perikanan baru melainkan juga dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, di tanah-tanah yang miring dibangun tanasering untuk menahan longsor. Pola penangkapan ikan juga diatur agar kelestariannya dijaga. Tanah-tanah terlantar, bekas tanaman kopi yang sudah tidak produktif lagi, ditanami dengan tanaman lain yang pengelolaannya diserahkan kepada para somah dengan pengawasan dari para menak/priyayi. Perburuan binatang diatur agar tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Semua kebijaksanaanya itu, dengan demikian, diarahkan untuk kemakmuran rakyat banyak yang diselaraskan dengan kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila beliau banyak sekali menerima perhargaan dari pemerintah kolonial Belanda, mulai dari bintang Gupermen sampai bintang dari Ratu Belanda.[32] Penghargaan dan pengakuan dari rakyat Sumedang sendiri diterimanya berupa pengakuan bahwa dia sebagai Bupati Pinilih, bupati yang terbaik dibanding bupati-bupati lainnya. Tindakan tersebut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Sumedang mulai dari somah sampai para menak/priyayi yang memiliki pertalian darah dengannya atau yang bekerja dalam lingkungan birokrasi pemerintahan kabupaten Sumedang.[33] Sebagai seorang bupati yang memperoleh pendidikan formal Belanda di sekolah kabupaten di Sumedang, yang dipimpin oleh seorang guru Belanda, Tuan Warnaar,[34] Pangeran Aria Suria Atmaja sangat besar perhatiannya terhadap dunia pendidikan formal dan informal. Pendidikan pesantren yang akan mendidik generasi muda berwawasan Islam didirikannya. Begitu juga dengan Sekolah Rakyat di desa, yang dengan rajin dikunjunginya terutama pada saat acara samen-an (pembagaian raport untuk kenaikan kelas), terus didorong agar bisa berkembang. Salah satu jasanya yang terbesar adalah dengan mendirikan Sekolah Pertanian di Tanjungsari, Sumedang dengan tujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik dan ahli yang akan menjadi pengembang pertanian rakyat di Sumedang. Rumahnya yang berada di Bandung dijadikan sebagai asrama bagi anggota keluarga dan golongan menak/priyayi dari Sumedang yang sedang bersekolah di kota itu. Sementara anggota menak/priyayi lainnya yang tidak bisa ditampung di asrama itu dititipkannya pada keluarga-keluarga Belanda yang dikenalnya dengan baik. Perhatiannya yang besar terhadap dunia pendidikan itu didasarkan atas visinya yang jauh ke depan, yaitu bahwa hanya dengan pendidikan, kemajuan masyarakat pada masa depan bisa diwujudkan. Dengan demikian, Pangeran Aria Suria Atmaja sebenarnya telah memainkan peranannya sebagai patron yang berpandangan baik dan modern, yang berusaha untuk memajukan dan mensejahterakan client-nya. Ia tidak semata-mata ingin mempertahankan status quo sebagai elite menak/priyayi melainkan juga berusaha untuk mengadakan transformasi sosial bagi kepentingan para pengikutnya, client, yaitu para somah dan golongan menak/priyayi lainnya. Gambaran tentang seorang patron yang berbakti kepada rakyatnya dapat dilihat dari keterangan para pembantu terdekatnya. Salah seorang di antaranya adalah R. Rangga Wangsadilaga, sebagai wedana Darmaraja yang selama kurang lebih 10 tahun bekerja dan berbakti di lingkungan pendopo kabupaten Sumedang, yang menyatakan sebagai berikut: Perkawis Kangjeng Pangeran mah moal aya anu nyaruaan dina ngajalankeunnana damel, kitu deui panganggona, dina damel anjeunna getol, jajim kana janji, surti, tigin, adil, jujur ka rakyat nu saestuna. Pangupa juwana, pangartina dipupujuhkeun, karahayuannana jeung kawaluyaannana dijaring. Salah sawios buktina kabupaten Sumedang sakieu makmurna, sanajan pasawahannana teu lega, tapi pepelakan tedaeun heunteu kurang, ingon-ingon loba, rakyatnya carukup, […].[35] Dengan demikian, Pangeran Aria Suria Atmaja, sebagai bupati yang menjalankan fungsi patron yang sebenarnya, telah berhasil membawa perubahan masyarakat ke arah kemajuan yang lebih baik. Dalam perspektif Sosiologi, peran yang dimainkannya itu menyebabkan terjadinya mobilitas sosial pada golongan-golongan masyarakat Sumedang sebagai client-nya.[36] Gambaran tentang adanya mobilitas sosial masyarakat Sumedang, terutama mobilitas vertikal, baik pada golongan petani somah maupun pada golongan menak/priyai, dapat dilihat dari adanya diversifikasi usaha yang berkembang di daerah ini sejak pemerintahan Pangeran Aria Suria Atmaja. Pada golongan menak/priyayi – yang memiliki kesempatan lebih banyak untuk memperoleh pendidikan formal – mobilitas sosial itu terjadi pada status pekerjaan mereka atau pada adanya diversifikasi pekerjaan, yang dari semula hanya sebagai pengikut bupati dengan berbagai hak tradisional yang dimilikinya kemudian menjadi pekerja di berbagai bidang yang tidak harus selalu berkaitan dengan lingkungan tradisional pendopo kabupaten. Pada golongan masyarakat inilah perubahan sosial itu cepat terjadi sejak pemerintahan bupati Pangeran Aria Suria Atmaja (1883-1919). Sementara itu pada golongan petani somah, pendapatan dari hasil pengelolaan sawah milik menak/priyayi, baik berupa maro ataupun mertelu,[37] dirasakan sudah tidak memadai lagi. Memang, keterikatan mereka terhadap para menak/priyayi sebagai patron-nya akan memberikan jaminan seumur hidup, artinya mereka tidak akan kekurangan pangan. Akan tetapi, karena kebutuhan hidup semakin meningkat, di mana nilai materi sudah bisa diukur dengan nilai uang,[38] mengerjakan tanah-tanah milik menak/priyayi itu dirasakan tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena dorongan itulah, timbul keinginan untuk mengembangkan usaha di bidang lain berupa diversifikasi usaha di luar sektor pertanian. Dorongan ke arah ini lebih besar lagi apabila dilihat dari kenyataan bahwa luas sawah dan kebun yang ada di kabupaten Sumedang sangatlah sempit. Diversifikasi usaha pertanian di Sumedang masih berkaitan dengan lingkungan agraris mereka. Misalnya beternak sapi, selain dimaksudkan untuk memperoleh nilai tambah ekonomi juga untuk membantu mengerjakan sawah. Kerajinan membuat pacul, bedog (golok), dan alat-alat pertanian lain adalah untuk kepentingan pertanian mereka sendiri, selain tentu saja untuk dijual ke daerah lain. Banyak juga petani yang menjadi pengrajin alat-alat dapur, anyam-anyaman, serta barang-barang lainnya dari kuningan. Bidang lain yang dikembangkan adalah tenun kentrung, pabrik oncom, dan kerajinan wayang golek, dan wayang kulit. Selain itu, banyak bidang usaha yang dikembangkan berkaitan dengan lingkungan dan gaya hidup menak/priyayi pada waktu itu. Peternakan kuda berkembang karena, selain ada usaha mendatangkan kuda dari Sumba oleh Pangeran Aria Suria Atmaja, juga seringnya diadakan perlombaan pacuan kuda serta kegiatan berburu dari para menak/priyayi yang suka menunggang kuda. Kerajinan membuat bedog, keris, dan bedil juga berkembang karena hal itu sangat dibutuhkan oleh para menak/priyayi untuk berburu rusa.[39] Di kota Sumedang, pada awal abad ke-20 para pedagang eceran sudah mulai tumbuh. Biasanya mereka berdagang di lingkungan pasar. Tidak diketahui apakah para pedagang tersebut berasal dari para petani yang berubah menjadi pedagang atau dari orang-orang keturunan Cina. Sektor informal juga sudah ada, yaitu para tukang cukur yang menempati emper-emper pinggir jalan, tukang dawet, tukang camcuah, dan tukang bubur kacang yang konsumennya bukan dari kalangan menak/priyayi saja melainkan juga dari lingkungan mereka sendiri. Kegiatan tersebut menambah kawasan tersendiri di sebelah timur pendopo kabupaten Sumedang, di luar lingkungan golongan menak/priyayi. Dalam skala makro, pada masa pemerintahan bupati Pangeran Aria Suria Atmaja, Sumedang mengalami kamajuan ekonomi yang pesat yang bisa dinikmati oleh sebagian besar rakyatnya. Kemajuan tersebut bukan hanya menyebabkan terjadinya mobilitas vertikal tetapi juga mobilitas horizontal. Kemajuan ekonomi di Sumedang juga telah mendorong migrasi penduduk dari luar Sumedang ke kota ini. Para petani Indramayu yang masih diwarisi oleh akibat buruk Tanam Paksa Tebu di daerahnya,[40] misalnya, banyak yang mencari pekerjaan di Sumedang. Oleh Kangjeng Pangeran, mereka dijadikan somah di daerah Tomo untuk mengolah sawah milik keluarga bupati pada tahun 1897.[41] Para petani dari Indramayu tersebut telah menjadi client baru yang bekerja untuk patron keluarga bupati Sumedang. Mereka menganggap hidup sebagai somah di Sumedang lebih baik dari pada hidup sebagai petani yang tidak memiliki tanah di Indramayu. Mobilitas sosial masyarakat Sumedang dan kemajuan ekonomi yang digambarkan oleh para pembantu Kangjeng Pangeran Aria Suria Atmaja, serta pengakuan pemerintah kolonial Belanda, ternyata tidak ditandai dengan tumbuhnya kelas pedagang yang tangguh di kota ini. Di daerah lain di Jawa, pada akhir abad 19 dan awal abad 20 adalah era tumbuhnya para pedagang Islam. Golongan ini kemudian masuk ke dalam Sarekat Dagang Islam yang kelak menjadi Sarekat Islam. Mobilitas sosial dan kemajuan ekonomi masyarakat Sumedang pada awal abad ke-20 lebih banyak ditandai oleh tumbuhnya pedagang kecil dan adanya diversifikasi usaha golongan petani somah di luar sektor agraria seperti kerajinan, peternakan, dan perdagangan dalam skala kecil. Sektor tersebut memberikan pendapatan yang lebih baik bila dibanding dengan pendapatan dari sektor pertanian. Ketidakmunculan golongan pedagang Islam yang kuat di daerah ini disebabkan oleh adanya anggapan tradisional bahwa status pedagang adalah rendah dan dipandang sebagai “orang pasar”. Pandangan ini mengindikasikan patronizing[42] dari kelompok menak/priyayi yang berkedudukan di pendopo kabupaten Sumedang yang telah biasa menerima upeti atau iuran dari orang-orang pasar tersebut. Di kalangan menak/priyayi Sumedang, mobilitas sosial terjadi dalam kaitannya dengan perubahan pekerjaan dan jabatan dari priyayi tradisional, priyayi karena turunan menak, dan menjadi priyayi professional yang bekerja di berbagai sektor modern di luar keterikatannya dengan tanah.[43] Mobilitas sosial mereka terjadi terutama dipengaruhi oleh dunia pendidikan, selain karena kebijaksanaan bupatinya seperti Pangeran Sugih dan Pangeran Aria Suria Atmaja. Memang, dunia pendidikan telah melandasi terjadinya mobilitas sosial. Sekolah yang dimasuki oleh anak-anak menak/priyayi Sumedang adalah Hollandsch Inlansche School (HIS) yang pada tahun 1907 didirikan di Sumedang. Sebelum ada HIS, anak-anak menak/priyayi Sumedang itu masuk ke Eerste School (Sekolah Angka Satu) yang hanya ada di Bandung. Sekolah ini memang hanya diperuntukkan bagi golongan menak/priyayi. Bagi anak golongan lain, di luar menak/priyayi, diperbolehkan masuk ke Tweede School (Sekolah Angka Dua) yang kemungkinan sudah ada di Sumedang sejak tahun 1892.[44] Sebelum itu, sebenarnya di Sumedang sudah ada juga Sekolah Desa yang boleh dimasuki oleh anak-anak dari golongan biasa, namanya Sakola Janggol,[45] yang inisiatif pendiriannya berasal dari Pangeran Sugih dan terus dikembangkan oleh Kangjeng Pangeran Aria Suria Atmaja. Sejak kesempatan bersekolah dibuka bagi berbagai golongan masyarakat, banyak menak/priyayi Sumedang yang bersekolah di luar kotanya. Tempat yang dipilih, selain kemungkinan di Batavia, adalah Bandung dan Bogor. Bupati Pangeran Aria Suria Atmaja sendiri selalu mendorong kepada semua golongan masyarakat untuk menempuh pendidikan formal, selain pendidikan pesantren yang ada di Sumedang. Para menak/priyayi yang ingin menjadi pamong praja, memilih sekolah di Bandung dan masuk ke Hoofdenschool, atau Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA).[46] Dan yang ingin menjadi guru, masuk ke Kweekschool, juga di Bandung. Bagi yang ingin memperdalam bidang pertanian, bisa masuk ke Landenbouwschool di Bogor yang sudah berdiri sejak tahun 1876. Dengan demikian, kesempatan bagi golongan menak/priyayi untuk meningkatkan kemampuannya di berbagai bidang terbuka dengan lebar. Hubungan yang baik antara bupati Pangeran Aria Suria Atmaja dengan pemerintah kolonial Belanda, serta dengan keluarga-keluarga Belanda di Bandung, semakin membuka kesempatan bagi para menak/priyayi dari Sumedang untuk bersekolah di sana. Selain ditempatkan di rumahnya yang kemudian dijadikan asrama, para menak/priyayi Sumedang juga banyak yang dititipkan di keluarga-keluarga Belanda di Bandung,[47] melalui hubungan patronase. Sebagai bupati pinilih, yang tidak membeda-bedakan rakyatnya, Pangeran Aria Suria Atmaja telah membuka kemungkinan terhadap warga biasa untuk bisa melanjutkan ke sekolah formal bagi golongan menak/priyayi. Anak petani yang bisa masuk ke sekolah Jonggol telah diberi kesempatan untuk mengadakan mobilitas sosial melalui penyerapan pengetahuan dari sekolah tersebut. Selain itu, di mata somah, gambaran tentang menak/priyayi adalah gambaran hidup yang serba enak karena dihormati oleh banyak orang, memiliki gelar, bisa bekerja di lingkungan pendopo dan, dengan demikian, bisa dekat dengan bupati. Melalui gambaran seperti itu bisa saja mendorong para somah untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah formal. Mobilitas sosial, paling tidak secara horizontal, terlihat juga dengan adanya sejumlah somah yang dari tempat tinggalnya bersekolah ke tempat di luar daerah mereka. Kecilnya pendapatan yang diperoleh dari tanah milik keluarga menak/priyayi – sehubungan dengan meningkatnya jumlah anggota keluarga yang memiliki hak waris tanah – telah mempengaruhi pandangan mereka untuk tidak terus-menerus tergantung pada tanah warisan. Ditambah lagi dengan kebijaksanaan Pangeran Aria Suria Atmaja, bupati pengganti Pangeran Sugih yang anaknya banyak itu, yang mewakafkan hampir seluruh tanahnya kepada Yayasan Pangeran Sumedang, menyebabkan akses golongan menak/priyayi Sumedang terhadap tanah semakin kecil. Kenyataan-kenyataan tersebut telah mendorong mereka untuk berprofesi atau bekerja di bidang lain dengan cara penempuh pendidikan terlebih dahulu untuk memperoleh pekerjaan yang bersifat formal. Pekerjaan tersebut bisa sebagai pamong praja sesuai dengan garis ke-menak/priyayi-annya, bisa juga di bidang lain yang lebih professional. Dengan demikian, pendidikan telah mendorong terjadinya mobilitas vertikal pada sebagian golongan menak/priyayi di Sumedang yang menempuh pendidikan serta memiliki profesi baru. Setelah banyaknya golongan menak/priyayi yang menempuh pendidikan profesional, sejak awal abad ke-20 telah lahir golongan “priyayi baru” di Sumedang. Lambang dari status mereka tidak lagi diukur dari keterikatannya dengan lingkungan pendopo atau luas tanah serta jumlah somah, melainkan dari latar belakang pendidikan. Pendidikan telah menjadi ukuran baru dalam menentukan status sosial seorang menak/priyayi.[48] Mereka bisa bekerja di lingkungan birokrasi yang memerlukan pendidikan formal tertentu, bisa juga di lingkungan lain yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, misalnya lingkungan pendidikan sebagai guru dan ahli hukum. Pekerjaan sebagai jaksa atau penghulu, yang dalam pemerintahan tradisional menjadi bagian dari birokrasi kabupaten Sumedang, bisa digolongkan ke dalam jenis profesi baru, sepanjang orang yang menjabatnya berlatar belakang pendidikan formal. Jenis pekerjaan seperti itu cukup banyak di Sumedang, sehingga di kota itu ada sebuah jalan yang sebagian besar penghuninya adalah para jaksa sehingga jalan tersebut dinamakan “Jalan Jaksa”.[49] Latar belakang “priyayi baru” bisa berasal dari “priyayi lama” yang memperoleh pendidikan formal, bisa juga berasal dari petani yang karena mobilitas sosialnya mampu bersekolah di lingkungan menak/priyayi.[50] Mereka bisa disebut sebagai golongan intelektual dan professional. Sebagai contoh adalah Raden Sadikin.[51] Dia adalah keturunan menak/priyayi Sumedang yang memperoleh pendidikan professional. Dia kemudian memilih Sekolah Pertanian di Bogor. Setelah tamat dari sana dia mengabdikan ilmu pertaniannya di Sekolah Pertanian Tanjungsari yang didirikan oleh bupati Pangeran Aria Suria Atmaja. Secara genealogis, dia adalah seorang menak, dan sebagai seorang professional dia termasuk ke dalam priyayi baru yang dilahirkan karena pendidikan. Gelar “Raden” yang disandangnya tidak harus mencerminkan sebagai turunan menak melainkan bisa saja karena jabatan dia sebagai professional di lingkungan akademik.[52] Kota Sumedang pada awal abad ke-20 masih mencerminkan sebuah kota yang dihuni oleh para menak/priyayi, baik menak/priyayi “lama” maupun menak/priyayi “baru”, serta sejumlah pedagang, baik pribumi maupun Cina yang bermukim di kawasan sebelah timur alun-alun kabupaten, sebagai kawasan yang terpisah dari lingkungan menak/priyayi yang menempati kawasan sebelah barat. Menurut Bezemer (1921),[53] penduduk kota Sumedang pada awal abad ke-20 adalah berjumlah 8.200 jiwa, termasuk 22 orang Eropa (seorang di antaranya adalah kontroleur Belanda) dan 200 orang turunan Cina. Sebagai akibat dari perubahan sosial, tidak semua menak/priyayi Sumedang bermukim di kota Sumedang. Banyak di antara mereka yang bermigrasi dan bermukim di Bandung serta kota-kota lainnya di Jawa Barat. Mereka yang tinggal di luar Sumedang selain yang memiliki mobilitas tinggi, seperti karena faktor pendidikan, juga adalah mereka yang anggota keluarganya diangkat menjadi pamongpraja di daerah lain. Sejak awal abad ke-20 banyak keluarga menak/priyayi Sumedang yang bermukim di Bandung, Cianjur, dan Garut serta kota-kota lainnya. Meskipun telah bermukim di kota lain, para menak/priyayi tersebut tetap memiliki keterikatan dengan Sumedang, baik karena faktor genealogis maupun kultural. Kota Sumedang telah menjadi pusatnya kebudayaan tradisional serta kebudayaan menak/priyayi “lama” dan menak/priyayi “baru”. Kebudayaan tradisional berpusat di lingkungan pendopo kabupaten. Keluarga menak/priyayi “lama” adalah yang mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan tersebut. Secara rutin di Srimanganti ditabuh gamelan Sunda yang didengarkan oleh kerabat keluarga bupati serta menak/priyayi lain. Ketika bupati Pangeran Aria Suria Atmaja menerima tamu agung, baik Belanda maupun pribumi, gamelan tersebut ditabuh. Maksudnya adalah untuk mengiringi pembicaraan.[54] Di sekitar Srimanganti secara rutin juga diadakan pertunjukan wayang yang bisa ditonton oleh penduduk kota dari alun-alun kabupaten. Tarian yang berkembang di Sumedang adalah tayub, yaitu tarian kesukaannya para menak/priyayi. Dalam tarian tersebut biasanya dilibatkan wanita cantik yang berfungsi sebagai pemikat para menak/priyayi. Tarian ini menjadi semacam gaya hidup tersendiri yang dianut dan berkembang di kalangan menak/priyayi.[55] Selain tayub, para menak/priyayi juga gemar melakukan olah raga berkuda. Pacuan kuda secara rutin diadakan di Sumedang. Dalam acara pacuan kuda ini juga biasanya dilakukan judi atau taruhan.[56] Di kalangan rakyat biasa, permainan yang berkembang adalah adu domba. Pangeran Aria Suria Atmaja sendiri sering menghadiri acara ini. Maksudnya adalah untuk mendekatkan diri dengan rakyatnya. Selain itu, berkembang juga acara lomba panahan yang biasanya diselenggarakan di tempat terbuka. Acara berburu, yang disebut bubujeng, dilakukan oleh keluarga menak/priyayi yang diiringi oleh para pengikutnya.[57] Terdapat perbedaan antara kesenian menak/priyayi “lama” dengan menak/priyayi “baru”. Golongan yang pertama itu masih berorientasi kepada kesenian tradisional. Pangeran Aria Suria Atmaja adalah sebagai salah seorang pelopornya. Dia masih sering melakukan dangding atau semacam pupuh Sunda yang dipuisikan. Sedangkan golongan yang terakhir, meskipun masih belum lepas dari selera berkesenian tradisional, telah memiliki gaya kesenian tersendiri. Kalau para menak/priyayi “lama” melakukan pertemuan dan perkumpulan di sekitar pendopo kabupaten, maka para menak/priyayi “baru” berkumpul di societeit.[58] Di tempat tersebut mereka biasanya melakukan tarian tayub. Selain itu, mereka juga berdansa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Pengaruh Barat tidak langsung mengubah adat-istiadat, tradisi, atau budaya berkesenian masyarakat. Sebagai contoh, tarian tayub yang dianggap sebagai tariannya para menak/priyayi, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari budaya agraris masyarakat pada umumnya serta budaya patronase golongan cacah pada khususnya. Tarian ini juga sering diselenggarakan di tempat-tempat terbuka pada acara selamatan hasil panen para petani yang menggarap tanah milik golongan menak/priyayi. Para petani menyelenggarakan acara ini sebagai bentuk persembahan untuk para menak/priyayi agar mau menari bersama wanita-wanita cantik setempat yang sengaja disediakan oleh para petani somah/cacah tersebut. Acara ini bisa dianggap sebagai persembahan para client terhadap para patron; atau sebagai pelengkap dari pemberian jasa tenaga kerja serta produksi hasil panen para petani somah/cacah terhadap para menak/priyayi.[59] Dalam kehidupan keluarga menak/priyayi, hubungan patronase yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat feodal agraris itu dimanfaatkan dengan baik oleh golongan menak/priyayi, terutama oleh para istri-istri mereka yang bertugas mendampingi suami. Sebagai pendamping suami menak/priyayi, mereka dihadapkan pada berbagai kesibukan dalam meningkatkan pengetahuan kewanitaan. Sebagai istri, mereka harus pandai dalam hal, misalnya saja, menerima tamu, mendampingi tamu, menata rumah, atau bergaul dengan golongan menak/priyayi lain, termasuk dengan orang-orang Belanda. Usaha untuk meningkatkan pengetahuan seperti itu banyak menyita waktu, termasuk dalam hal mempraktekkannya dalam kehidupan rumah tangga mereka yang penuh dengan berbagai macam norma, adat, dan tradisi. Oleh karena itu, bagi istri-istri yang punya bayi balita (di bawah lima tahun) tidak akan memiliki cukup waktu untuk menyusui anaknya. Tugas tersebut biasanya diserahkan kepada orang lain yaitu golongan somah/cacah yang memiliki anak seusia. Bagi istri-istri menak/priyayi, mencari ibu susu adalah merupakan pekerjaan yang sangat mudah, sebab bagi ibu susu yang ditugasi untuk melakukan pekerjaan demikian akan merupakan kebanggaan tersendiri. Pekerjaan tersebut bisa dianggap sebagai adanya pengakuan golongan menak/priyayi terhadap somah/cacah. Dalam kerangka hubungan patronase, pekerjaan ibu susu dianggap sebagai pemberian jasa client terhadap patron-nya. Dengan demikian, dalam hubungan patronase seperti ini, pemberian jasa telah meluas sampai pada lingkungan yang lebih dalam, yakni kepada lingkaran kehidupan keluarga menak/priyayi. Akibat dari hubungan seperti itu, dalam jangka panjang, telah melahirkan ikatan kekeluargaan yang lebih kompleks, termasuk dalam “peningkatan” status sosial seseorang.[60] Bagi seorang anak somah/cacah yang ibunya dijadikan sebagai ibu penyusu (ibu susu) anak turunan menak/priyayi atau keluarga bupati, akan memiliki kebanggaan tersendiri karena dia menjadi saudara sesusu dengan anak menak/priyayi itu. Dan karenanya dia juga bisa bergaul dengan leluasa bersama saudara sesusunya itu. Kadang-kadang anak-anak somah/cacah yang bersaudara susu dengan anak menak/priyayi itu mendapatkan kesempatan untuk masuk sekolah formal seperti anak menak/priyayi tersebut. Biasanya yang menanggung biaya sekolah anak itu adalah keluarga menak/priyayi yang telah dibantu dalam proses penyusuan tersebut. Setelah lulus sekolah, anak inipun akan mendapatkan kesempatan mobilitas sosial yang sama dengan anak menak/priyayi, misalnya bekerja di sektor formal, sebagai guru, yang dipandang sebagai pekerjaan terhormat dan biasanya hanya dilakukan oleh seorang turunan menak/priyayi secara genealogis.[61] Mobilitas sosial seperti itu mengingatkan kita pada proses lahirnya golongan priyayi rendahan dalam masyarakat Jawa seperti digambarkan oleh Umar Kayam (1992) dalam novelnya yang terkenal, Para Priyayi.[62] Dari novel tersebut dapat dilihat bagaimana patronase antara petani wong cilik dengan keluarga priyayi sebagai patronnya telah berpengaruh terhadap timbulnya mobilitas sosial secara vertikal, yang ditandai dengan lahirnya golongan priyayi rendahan baru, anak wong cilik yang menjadi guru (priyayi), seperti tokoh Sastrodarsono, yang diberi kesempatan yang sama dengan anak priyayi untuk sekolah di sekolah formal. Dengan demikian, hubungan patronase seperti itu juga telah melahirkan mobilitas sosial pada golongan somah/cacah di Sumedang pada awal abad ke-20, meskipun jumlah yang mengalami mobilitas seperti itu tidak banyak. Konflik yang kadang-kadang timbul di antara sesama keluarga menak/priyayi biasanya disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, karena masalah perkawinan antara menak/priyayi “darah biru” dengan menak/priyayi “baru” yang lahir karena mobilitas sosial, achieved status. Konflik antar keluarga menak/priyayi itu,[63] yang disebabkan oleh berbagai masalah, masih dapat diatasi oleh mereka sendiri, sehingga tidak mengganggu kehidupan sosial-budaya atau tatanan kehidupan kabupaten sebagai pusat kebudayaan. Kabupaten sebagai pusat pemerintahan masih tetap bisa menampilkan kebesaran-kebesarannya baik terhadap rakyat maupun terhadap pemerintah kolonial Belanda. Untuk menampilkan wajah kabupaten sebagai pusat kebudayaan, dilakukan berbagai upaya ritual, pertunjukkan seni, dan acara religius peringatan hari besar agama Islam. Pada masa pemerintahan Pangeran Aria Suria Atmaja, misalnya, tiap tahun diselenggarakan muludan atau peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW secara besar-besaran di pusat pemerintahan, di pendopo kabupaten Sumedang. Selain itu, pertunjukan wayang golek secara rutin diadakan di sekitar pendopo dan alun-alun kabupaten Sumedang yang bisa disaksikan oleh berbagai golongan masyarakat. Setiap hari Minggu, gamelan degung yang berada di atas panggung terus ditabuh oleh para nayaga. Untuk para menak/priyayi, sering disuguhkan tarian tayub dengan diiringi lagu-lagu yang juga dinyanyikan oleh Kangjeng Pangeran Aria Suria Atmaja sendiri, seperti lagu sonteng yang menjadi kegemarannya.[64] Dengan semua acara tersebut diharapkan agar rakyat dari berbagai golongan bisa terhibur dan bisa melupakan segala masalah kehidupan yang dihadapi mereka setiap hari. Dalam konteks yang lebih luas, semua acara tersebut bisa dianggap sebagai upaya bupati untuk mengkomunikasikan otoritas, kekuasaan, dan kepemimpinannya sebagai patron kepada sejumlah besar client yang menjadi bawahannya, sehingga semua golongan masyarakat berada dalam tatanan sosial-budaya kabupaten yang ingin ditegakkannya. PenutupDari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya mobilitas sosial di kalangan menak/priyayi Sumedang disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, faktor pendidikan; yang telah berpengaruh terhadap pembentukan sikap, watak, dan profesi baru bagi mereka yang memperoleh kesempatan untuk itu. Golongan masyarakat yang berhasil menempuh tingkat pendidikan setinggi-tingginya memiliki profesi baru yang sebelumnya tidak ada dalam tatanan masyarakat tradisional di Sumedang. Kelompok ini menjadi golongan profesional baru yang bekerja di luar lingkungan ke-menak/priyayi-annya. Dengan bekerja di Binnenlandsch Bestuur atau di bidang lain, misalnya, kelompok ini mendapat penghasilan yang relatif besar, status, dan prestise sosial yang tinggi. Kedua, akibat semakin sempitnya lahan tanah yang dimiliki keluarga menak/priyayi yang berkaitan dengan semakin kecilnya pendapatan dari tanah pertanian, mendorong mereka untuk bekerja di bidang lain, yang sebelumnya harus menempuh pendidikan terlebih dahulu. Dan ketiga, kebijaksanaan para bupati Sumedang seperti, antara lain, bupati Pangeran Aria Suria Atmaja yang berperan sebagai patron di daerahnya telah mendorong penduduk Sumedang untuk menempuh pendidikan formal setinggi-tingginya sehingga menyebabkan terjadinya mobilitas sosial baik secara vertikal maupun horizontal, terutama dengan melalui jenjang pendidikan bagi mereka yang menempuhnya. DAFTAR PUSTAKA Bremen, Jan. 1983. Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa pada Masa Kolonial. Terjemahan. Jakarta: LP3ES. Evers, Hans-Dieter dan Tilman Schiel. 1990. Kelompok-kelompok Strategis. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Geertz, Clifford. 1963. Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley: University of California Press. Kartadibrata, R.M. Abdullah. 1989. Riwayat Pangeran Aria Soeria Atmadja. Sumedang: Penerbitan Yayasan Pangeran Sumedang. Kartadibrata, R.M. Abdullah. 1989. Riwayat Leluhur Sumedang. Sumedang: Penerbitan Yayasan Pangeran Sumedang. Kartodirdjo, Sartono. 1984. Ratu Adil. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Kartodirdjo, Sartono. 1985. “Bureaucracy and Aristocracy: The Indonesian Experiences in the XIXth Century” dalam Modern Indonesia: Tradition and Transformation. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Kartodirdjo, Sartono. 1985. “The Regent of Java as Middleman” dalam Modern Indonesia: Tradition and Transformation. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Kartodirdjo, Sartono. 1988. Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Jilid I: Dari Emporium hingga Imperium. Jakarta: PT Gramedia. Kartodirdjo, Sartono. 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Jilid 2: Dari Kolonialisme hingga Nasionalisme. Jakarta: PT Gramedia. Kaufman, Robert R.. 1974. “The Patron-Client Concepts and Macro-Politics: Prospecs and Problems” dalam Comparative Studies in Sociology and History. Kayam, Umar. 1992. Para Priyayi: Sebuah Novel. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. Koentjaraningrat (Ed.). 1964. Masjarakat Desa di Indonesia. Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Lauer, Robert H.. 1993. Perspektif tentang Perubahan Sosial. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Pers. Leirissa, R.Z.. 1985. Terbentuknya Sejarah Masyarakat Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Moertono, Soemarsaid. 1968. State and the Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century. Ithaca, New York: Cornell University Press. Niel, Robert van. 1984. Munculnya Elit Modern Indonesia. Terjemahan. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. Onghokham. 1983. Rakyat dan Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Scherer, Savitri Prastiti. 1985. Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad ke-20. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Schrieke, B.J.O.. 1955. “The Native Rulers” dalam Indonesian Sociological Studies, Vol.I. The Hague and Bandung: W. van Hoeve Ltd.. Scott, James C.. 1972. “The Erotion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia” dalam Journal of Asian Studies, No.XXXII. November. Seligman, Lester G.. 1989. “Perekrutan Kaum Elite” dalam Zainal AK (Ed.). Elite dan Modernisasi. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Pers. Sugandi, Didih. 1994. “Leluhur Pangeran Soeria Atmadja”. Makalah. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung, Oktober. Tjondronegoro, Sediono M.P.. 1983. Dua Abad Penguasaan Tanah. Jakarta: PT Gramedia. Wiriaatmadja, Rochiati. 1994. “Pengaruh Pendidikan terhadap Golongan Elite Sunda di Priangan Timur (Sumedang, Tasikmalaya, dan Ciamis)”. Makalah. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung, Oktober. Wiriaatmadja, Rochiati. 1995. “Pengaruh Pendidikan Barat terhadap Golongan Elite Tradisional Sunda”. Laporan Penelitian. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung. Wiyanarti, Erlina. 1994. “Perkembangan Perekonomian di Keresidenan Priangan”. Makalah. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung, Oktober. WAWANCARA Abdullah Kartadibrata, R.M.. Keturunan Menak Sumedang dan Pengurus Yayasan Pangeran Sumedang. Sumedang: 15 Oktober 1994. Djamhir Soemawilaga, Drs.H.. Pengurus Yayasan Pangeran Sumedang. Sumedang: 11 Mei 1994. Sartika. Keturunan Menak Sumedang dan Pengurus Museum Geusan Ulun Sumedang. Sumedang: Juli 1994. Sufia Isa, Dra.. Keturunan Menak Sumedang dan Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung. Bandung: Mei 1994. Syafii Suryagunawan. Pengurus Yayasan Pangeran Sumedang. Sumedang: Juli 1994. Yusuf. Pengurus Yayasan Pangeran Sumedang. Sumedang: Juli 1994. *)Dr. Nana Supriatna, M.Ed. adalah Staf Pengajar di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI [1]Soemarsaid Moertono, State and the Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1968). [2]R.M. Abdullah Kartadibrata, Riwayat Pangeran Aria Soeria Atmadja (Sumedang: Penerbitan Yayasan Pangeran Sumedang, 1989). [3]Wawancara dengan R.M. Abdullah Kartadibrata, Keturunan Menak Sumedang dan Pengurus Yayasan Pangeran Sumedang (Sumedang: 15 Oktober 1994). [4]R.M. Abdullah Kartadibrata, Riwayat Leluhur Sumedang (Sumedang: Penerbitan Yayasan Pangeran Sumedang, 1989). [5]Didih Sugandi, “Leluhur Pangeran Soeria Atmadja”, Makalah (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung, Oktober 1994), hlm.4. [6]Sartono Kartodirdjo, “Bureaucracy and Aristocracy: The Indonesian Experiences in the XIXth Century” dalam Modern Indonesia: Tradition and Transformation (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm.129-49. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pengangkatan bupati Sumedang bukan hanya didasarkan atas garis genealogis melainkan juga atas kemampuan serta potensi pribadinya. [7]Sartono Kartodirdjo, “The Regent of Java as Middleman” dalam Modern Indonesia: Tradition and Transformation (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm.150-54. [8]Ibid., hlm.144. [9]Jumlah penduduk kabupaten Sumedang pada tahun 1905, menurut catatan T.J. Bezemer dalam Beknopte Encyclopedie van Nederlandsch-Indie (1921), adalah sebanyak 274.000 jiwa. Selanjutnya lihat Erlina Wiyanarti, “Perkembangan Perekonomian di Keresidenan Priangan”, Makalah (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung, Oktober 1994), hlm.23. [10]B.J.O. Schrieke, “The Native Rulers” dalam Indonesian Sociological Studies, Vol.I (The Hague and Bandung: W. van Hoeve Ltd., 1955), hlm.172-73. [11]Rochiati Wiriaatmadja, “Pengaruh Pendidikan terhadap Golongan Elite Sunda di Priangan Timur (Sumedang, Tasikmalaya, dan Ciamis)”, Makalah (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung, Oktober 1994), hlm.22. Lihat juga Rochiati Wiriaatmadja, “Pengaruh Pendidikan Barat terhadap Golongan Elite Tradisional Sunda”, Laporan Penelitian (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung, 1995). [12]Lihat Sediono M.P. Tjondronegoro, Dua Abad Penguasaan Tanah (Jakarta: PT Gramedia, 1983). [13]Clifford Geertz, Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia (Berkeley: University of California Press, 1963). [14]Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Jilid I: Dari Emporium hingga Imperium (Jakarta: PT Gramedia, 1988), hlm.152. [15]Ibid., hlm.248. [16]R.M. Abdullah Kartadibrata, 1989, Riwayat Leluhur Sumedang … Op.Cit., hlm.25-37. [17]Ibid.. [18]Priyayi atau “adik raja” adalah merupakan pengertian “priyayi lama” untuk membedakannya dengan pengertian “priyayi baru”. Selanjutnya lihat Robert van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia, Terjemahan (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984). [19]Tidak diketahui dengan pasti apakah semua tanah yang digarap petani dimiliki oleh para menak atau priyayi kabupaten Sumedang. [20]Lihat R.M. Abdullah Kartadibrata, 1989, Riwayat Pangeran Aria … Op.Cit., hlm.22. [21]Ibid., hlm.23-46. [22]Wawancara dengan Sartika, Keturunan Menak Sumedang dan Pengurus Museum Geusan Ulun Sumedang (Sumedang: Juli 1994). [23]Sartono Kartodirdjo, Ratu Adil (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984), hlm.47. [24]Wawancara dengan Syafii Suryagunawan, Pengurus Yayasan Pangeran Sumedang (Sumedang: Juli 1994). [25]Wawancara dengan Yusuf, Pengurus Yayasan Pangeran Sumedang (Sumedang: Juli 1994). [26]Sartono Kartodirdjo, 1984, Op.Cit., hlm.41-2. Lihat juga Koentjaraningrat (Ed.), Masjarakat Desa di Indonesia (Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964). [27]Stratifikasi berdasarkan akses terhadap tanah pada masyarakat pedesaan ini mirip dengan stratifikasi masyarakat di pedesaan Jawa yang digambarkan oleh Sartono Kartodirdjo yaitu sebagai kuli kenceng (pemilik), kuli ngindung (penyewa tanah), dan kuli ngindung tlosor (buruh tani atau pekerja upahan). Selanjutnya lihat Sartono Kartodirdjo, 1984, Loc.Cit.. [28]Soemarsaid Moertono, 1968, Op.Cit., hlm.98. [29]Onghokham, Rakyat dan Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983), hlm.64. [30]R.M. Abdullah Kartadibrata, 1989, Riwayat Leluhur Sumedang … Loc.Cit.. [31]R.M. Abdullah Kartadibrata, 1989, Riwayat Pangeran Aria … Loc.Cit.. [32]Ibid.. [33]Wawancara dengan Drs.H. Djamhir Soemawilaga, Pengurus Yayasan Pangeran Sumedang (Sumedang: 11 Mei 1994). [34]R.M. Abdullah Kartadibrata, 1989, Riwayat Pangeran Aria … Op.Cit., hlm.27. Lihat juga Rochiati Wiriiatmadja, 1995, Op.Cit., hlm.80. [35]Artinya: “Mengenai Kangjeng Pangeran [bila dibandingkan dengan bupati lain], ia lebih giat dalam bekerja, selalu menepati janji, penuh perhatian, adil dan jujur terhadap rakyatnya. Penghasilan dan ilmunya dimanfaatkan untuk rakyat dan ia sendiri mampu menjaga dirinya dengan baik. Salah satu buktinya kabupaten Sumedang menjadi kabupaten yang makmur, walaupun luas sawahnya terbatas. Bahan makanan tidak kurang, ternak cukup banyak, dan rakyat hidup dengan berkecukupan”. Selanjutnya lihat R.M. Abdullah Kartadibrata, 1989, Riwayat Pangeran Aria … Op.Cit., hlm.29. Menurut Rochiati Wiriaatmadja, Pangeran Aria Suria Atmaja telah menunjukkan karakter patron yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modern menjadi satu sistem nilai pribadi yang serasi (blending traditional and modern values harmoniously) dan menjadi bupati yang, dalam bahasa Sunda, toweksa, welas asih ka sasama, jeung ngenak-ngenak ati kuring. Selanjutnya lihat Rochiati Wiriaatmadja, 1995, Op.Cit., hlm.80. [36]Nampaknya bupati Pangeran Aria Suria Atmaja telah memerankan peran sebagai agent of change dan sebagai bagian dari kelompok strategis yang berperan dalam reformasi masyarakatnya. Tentang konsep agent of change dan kelompok strategis dalam kajian Sosiologi, lihat Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, Terjemahan (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm.347; dan Hans-Dieter Evers dan Tilman Schiel, Kelompok-kelompok Strategis, Terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm.9-19. [37]Maro dan mertelu adalah istilah dalam bahasa Sunda mengenai pembagian hasil panen. Maro adalah membagi hasil panen setengah untuk pemilik dan setengahnya lagi untuk pengarap. Sedangkan mertelu, hasil panen dibagi tiga dengan dua pertiga diserahkan kepada pemilik, sedangkan penggarap hanya satu pertiganya. [38]Menurut Sartono Kartodirdjo, desa-desa di Indonesia yang hidup dalam tatanan ekonomi agraris tradisional sudah dimasuki kehidupan ekonomi uang sejak Zaman Liberal tahun 1870. Selanjutnya lihat Sartono Kartodirdjo, 1987, Op.Cit., hlm.318-34. [39]Lihat R.M. Abdullah Kartadibrata, 1989, Riwayat Pangeran Aria … Op.Cit., hlm.24-30. [40]Jan Bremen, Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa pada Masa Kolonial, Terjemahan (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm.125-36. [41]R.M. Abdullah Kartadibrata, 1989, Riwayat Pangeran Aria … Op.Cit., hlm.37. [42]Rochiati Wiriaatmadja, 1995, Op.Cit., hlm.82. [43]Van Niel menyebut kelompok ini sebagai homines novi atau “orang-orang baru” dalam pandangan dan profesi pekerjaan. Selanjutnya lihat Robert van Niel, 1984, Loc.Cit.. [44]Dari berbagai Sekolah Dasar disistematisasikan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi dua jenis pada tahun 1892. Selanjutnya lihat R.Z. Leirissa, Terbentuknya Sejarah Masyarakat Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985), hlm.25-6. [45]Wawancara dengan Syafii Suryagunawan, Pengurus Yayasan Pangeran Sumedang (Sumedang: Juli 1994). [46]Hoofdenschool telah ada di Bandung sejak tahun 1876 yang kemudian berubah namanya menjadi OSVIA pada tahun 1899. Selanjutnya lihat Sartono Kartodirdjo, 1987, Op.Cit., hlm.355. [47]R.M. Abdullah Kartadibrata, 1989, Riwayat Pangeran Aria … Loc.Cit.. [48]Kelompok menak/priyayi Sumedang yang jumlahnya kecil ini terbentuk karena perjuangan, prestasi, dan kualifikasi pendidikan. Oleh akrena itu memberikan kebanggaan bagi mereka yang menyandangnya. Selanjutnya lihat Savitri Prastiti Scherer, Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad ke-20, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985), hlm.41. [49]Wawancara dengan Dra. Sufia Isa, Keturunan Menak Sumedang dan Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung (Bandung: Mei 1994). [50]Sartono Kartodirdjo menyebut golongan ini sebagai homines novi atau orang yang mencapai status priyayi melalui jenjang pendidikan dan memperoleh status lebih tinggi dibandingkan dengan status sebelumnya. Lihat Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Jilid 2: Dari Kolonialisme hingga Nasionalisme (Jakarta: PT Gramedia, 1990), hlm.87-90 [51]Raden Sadikin adalah ayah dari Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966-1977. [52]Para priyayi baru dengan gelar Raden atau Raden Mas lebih berkaitan dengan kedudukan administrasi tertentu, bukan karena garis keningratan. Lihat Robert van Niel, 1984, Op.Cit., hlm.41. [53]T.J. Bezemer, Beknopte Encyclopedie van Netherlandsch Indie (1921), sebagaimana dikutip oleh Erlina Wiyanarti, 1994, Loc.Cit.. [54]Wawancara dengan Sartika, Keturunan Menak Sumedang dan Pengurus Museum Geusan Ulun Sumedang (Sumedang: Juli 1994). [55]Menurut Suryagunawan, pada mulanya tayub di Sumedang itu dimaksudkan untuk mengembangkan agama Islam. Dipilihnya wanita cantik dalam tarian tersebut adalah untuk menarik orang lain agar masuk ke dalam agama Islam. Dengan cara menari bersama wanita cantik itu diharapkan agar orang-orang bisa dibujuk untuk masuk Islam. Masuknya unsur-unsur pornografi dalam tari tayub itu disebabkan karena orang-orang Belanda yang juga tertarik dengan tarian tersebut, mulai mengintervensi corak tarian tersebut. Wawancara dengan Syafii Suryagunawan, Pengurus Yayasan Pangeran Sumedang (Sumedang: Juli 1994). [56]Wawancara dengan Dra. Sufia Isa, Keturunan Menak Sumedang dan Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung (Bandung: Mei 1994). [57]Wawancara dengan Sartika, Keturunan Menak Sumedang dan Pengurus Museum Geusan Ulun Sumedang (Sumedang: Juli 1994). [58]Wawancara dengan Dra. Sufia Isa, Keturunan Menak Sumedang dan Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung (Bandung: Mei 1994). [59]Lahan pertanian di Sumedang yang sempit berpengaruh juga terhadap pendapatan petani somah/cacah; dan oleh karena itu mereka harus tetap mempertahankan ikatan vertikalnya dengan para menak/priyayi sebagai patron. Dengan demikian, sistem patronase diperkuat oleh kondisi sosial-ekonomi. Mengenai hal ini lihat, misalnya, James C. Scott, “The Erotion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia” dalam Journal of Asian Studies, No.XXXII (November 1972), hlm.8. [60]Menurut Kaufman, dalam masyarakat pedesaan tradisional hubungan patronase bukan hanya bersifat dyadic atau hubungan timbal-balik, melainkan juga hubungan yang bersifat kompleks yang melibatkan berbagai pelaku yang berlapis-lapis. Hubungan dalam struktur keluarga menak/priyayi Sumedang seperti itu mengindikasikan kompleksnya hubungan-hubungan tersebut. Selanjutnya lihat Robert R. Kaufman, “The Patron-Client Concepts and Macro-Politics: Prospecs and Problems” dalam Comparative Studies in Sociology and History (1974), hlm.284-308. [61]Wawancara dengan Dra. Sufia Isa, Keturunan Menak Sumedang dan Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung (Bandung: Mei 1994). [62]Umar Kayam, Para Priyayi: Sebuah Novel (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1992), khususnya pada subjudul “Sastrodarsono”. [63]Konflik dalam antar golongan elit menak/priyayi yang terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu lebih banyak terjadi karena masalah perekrutan mereka dalam menduduki jabatan yang didasarkan atas ikatan patronase (untuk golongan menak/priyayi “lama”) serta kemampuan profesional (untuk menak/priyayi “baru”). Selanjutnya lihat Lester G. Seligman, “Perekrutan Kaum Elite” dalam Zainal AK (Ed.), Elite dan Modernisasi, Terjemahan (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm.15-30. [64]R.M. Abdullah Kartadibrata, 1989, Riwayat Leluhur Sumedang … Op.Cit., hlm.27. |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Periklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 berikutyang Inc.