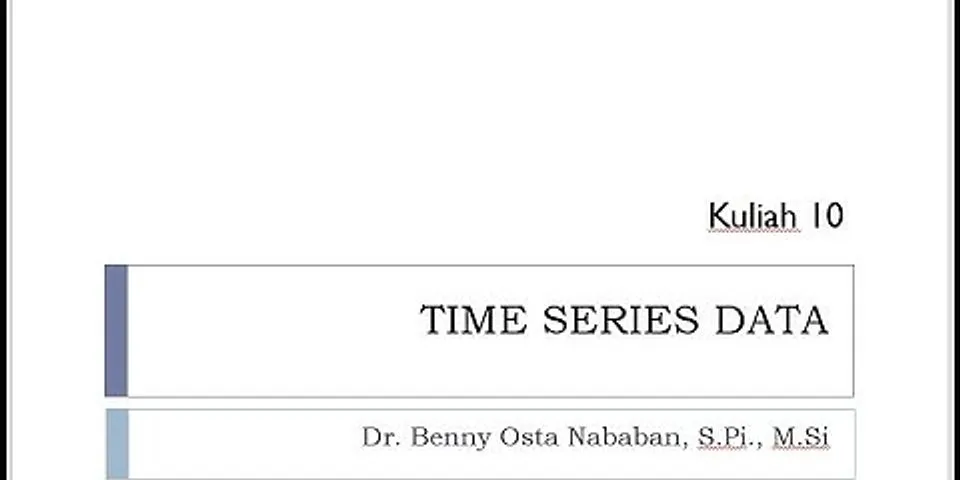KoranNTB.com – Mantan politikus Demokrat, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang angkat bicara soal polemik istilah kafir pada non-muslim. Menurut TGB, kesepakatan ulama istilah kafir dari sisi akidah berlaku pada siapapun yang tidak percaya atau ingkar pada Allah dan rasulnya, serta pokok-pokok syariat Islam. Namun, kata TGB, dalam muamalah Rasulullah mengajarkan umatnya untuk membangun hubungan saling menghormati dengan semua orang. “Rasul Shallallahu Alayhi Wasallam menyepakati piagam bernegara bersama seluruh komponen di Madinah,” tulis TGB melalui halaman Facebook resminya. Katanya, dalam piagam itu ada hak dan kewajiban yang sama. Kata kafir tidak digunakan dalam piagam itu untuk menyebut kelompok-kelompok Yahudi yang ikut dalam kesepakatan itu. Karena piagam Madinah bukan tentang prinsip akidah tapi tentang membangun ruang bersama untuk semua. “Sekarang kita hidup di negara-bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan salah satu bentuk persaudaraan yang wajib dijaga dengan sesungguh hati dan sekuat-kuatnya adalah persaudaraan sebangsa, ukhuwah wathaniyah,” ungkapnya. Dijelaskan, penyebutan kepada saudara sebangsa harus berpijak pada semangat persatuan dan persaudaraan. “Maka menyebut orang yang beragama lain dengan sebutan non muslim tidak keliru dan bahkan lebih sesuai dengan semangat kita berbangsa,” ucapnya. TGB juga mengatakan, dalam beragam acara publik, saat seorang muslim memimpin doa dia mengawali dengan ucapan, ‘ijinkan saya membaca doa secara Islam dan bagi saudara yang non muslim agar menyesuaikan’. “Kalau kata non muslim diganti kafir tentu sangat tidak nyaman untuk saudara-saudara yang beragama selain Islam,” papar Koordinator bidang Keumatan Golkar ini. Dia juga membagikan sebuah foto di halaman, yang memperlihatkan penanda saat akan memasuki Kota Mekkah. Petunjuk jalan tersebut jelas tertulis non muslim dengan bahasa Arab, bukan tertulis kafir. (red/7) BACA: Soal Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Dinilai Pilih Kasih
LADUNI.ID, Jakarta - Memang benar ada kata kafir pada piagam Madinah, tapi kata tersebut tidak ditujukan kepada warga dan penduduk Madinah. Piagam Madinah terdiri dari 63 poin. Poin 1 sampai poin 3 berupa pembukaan. Poin 4 sampai poin 19 khusus membahas hak hak dan kewajiban umat Islam yaitu kaum Muhajirin dan Anshar. Dari poin dua puluh baru membahas keikutsertaan orang orang Yahudi. Penyebutan kata kafir ada pada poin 17. Poin tersebut bisa diterjemahkan sebagai berikut: ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن‘Seorang mukmin tidak (diperkenankan) membunuh orang beriman lainnya lantaran ia (membunuh) orang kafir. Dan tidak (pula) orang mukmin menolong orang kafir (lantaran ia membunuh) orang beriman’. Poin ini tidak sedang membahas orang-orang Yahudi atau pemeluk agama lainnya. Dr. Hasan Muhyiddin Al-Qadiry dalam disertasinya setebal seribu halaman tentang isi piagam Madinah dan perbandingannya dengan sistem pemerintahan negara Inggris, Eropa dan Amerika menjelaskan bahwa kata kafir pada poin tersebut ditujukan kepada ‘musuh Islam dan musuh Negara Madinah’. Menekankan pentingnya menjaga keamanan dan pertahanan bersama, dan tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin yang berada di negara aman berupa Negara Madinah ini membunuh atau memusuhi orang mukmin lain atau warganegara lain lantaran orang mukmin tersebut membunuh ‘musuh yang menyerang’ negara Madinah. Dan tidak pula menolong orang kafir yang seorang musuh ini lantaran dia membunuh orang mukmin atau warga negara Madinah lainnya. Kesimpulannya, penyebutan kata kafir pada poin 17 ini erat kaitannya dengan penjagaan keamanan negara Madinah dan ditujukan kepada ‘musuh luar’ yang berpotensi menyerang. Bukan kepada warga Negara Madinah yang tidak beragama Islam karena mereka terkecualikan dari poin ini. Poin ini lebih dominan ditujukan kepada kafir Quraisy yang waktu itu masih memusuhi dan mengadu domba umat Islam bahkan ketika kaum Muhajirin posisinya sudah berada di Madinah. Maka walaupun kata kafir disebutkan dalam piagam Madinah tetapi Rasulullah dan umat Islam tidak menggunakannya dalam memanggil orang yang tidak mau masuk Islam. Untuk memanggil orang Yahudi dan Nasrani ada istilah lain yaitu Ahlu kitab. Tidak ada penggunaan kata kafir di sini bukan berarti menghapus atau mengubah ayat-ayat Al Qur’an yang mengandung istilah kafir, karena ini ranah teologis yang sudah baku, sementara penggunaannya dalam sehari hari masuk ke ranah fiqh mu’amalah dan fiqh berkewarganegaraan. (Sumber: Islam Moderat)
Kafir. Kata ini sangat terkait dengan akidah Islam. Apa itu kafir? Secara bahasa, di dalam Kamus Al-Mujam al-Wasith (II/891), orang kafir dimaknai sebagai “siapa saja yang tidak mengimani keesaan Allah, atau kenabian Muhammad saw., atau risalah Islam, atau ketiga-tiganya”. Secara syar’i, “Kafir adalah siapa saja yang tidak mengimani Allah dan Nabi Muhammad saw., atau siapa saja yang mengingkari ajaran apa pun yang diketahui secara pasti berasal dari Islam, atau yang merendahkan kedudukan Allah dan risalah Islam.” Demikian antara lain ditulis oleh Prof. Rawwas Qal’ah Jie (Mujam Lughah al-Fuqaha`, hlm. 268). Dengan demikian kafir dengan non-Muslim memang maknanya sama. Istilah sakral ini lalu ditetapkan untuk diganti dengan ‘non-Muslim’ atau ‘muwathinun’ (warga negara). Katanya, itu hasil Munas Ulama dan Musyarawah Besar NU pada tahun 2019. Sontak saja reaksi pun datang dari berbagai penjuru. Aneh memang, pandangan seperti itu diklaim sebagai pendapat ulama. Padahal para ulama salaf justru berpandangan sebaliknya. Sebut saja, Imam an-Nawawi. Beliau menuturkan, “Orang yang tidak mau mengkafirkan para pemeluk agama selain Islam seperti Nasrani, atau ragu dengan kekufuran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir meskipun pada saat itu dia mengaku Islam dan yakin dengan hal itu.” (An-Nawawi, Rawdhah ath-Thalibin, X/70). “Untung saja ada klarifikasi bahwa itu bukan pandangan ulama,” ungkap Pak Zulkifli. Barangkali yang beliau maksud adalah pernyataan Habib Taufiq. “Saya tidak ingin sampeyan larut dalam masalah ini. Panggilan kafir, non-Muslim, perhatikan, itu bukan keputusannya ulama. Itu komentarnya dua orang saja. Profesor-profesor ini. Jadi, itu bukan keputusan ulama NU. Hati-hati,” ungkap Habib Taufiq bin Abdul Qadir bin Husein Assegaf, Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (6/3/2019). Hal ini wajar belaka. Pasalnya, pimpinan komisi yang membahas perkara tersebut adalah Abdul Moqsith Ghazali. Dia selama ini dikenal sebagai tokoh liberal. Alasan yang diungkapkan, ini negara bangsa bukan negara agama. Karena itu tidak ada istilah kafir harbi, kafir dzimmi, kafir mu’ahid dan kafir musta’man. “Lha, kalau bukan negara agama mengapa menggunakan dalih agama untuk menghilangkan istilah dalam agama, dalam hal ini istilah kafir?” ujar Ustadz Anwar dengan nada tinggi. “Iya, ini artinya mengadili ajaran agama oleh ajaran manusia. Istilah kafir itu kan istilah Islam. Namun, istilah itu diadili oleh istilah dalam negara bangsa,” Pak Iman menanggapi. “Salah kacamata,” tambahnya. Saya sampaikan kepada mereka, “Ini cara berpikir rancu dari dasarnya. Pertama: Dasar berpikirnya adalah sekular, yakni memisahkan agama dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua: Mengotak-atik istilah Islam untuk disesuaikan dengan konsep bukan Islam.” Saya sampaikan pula perkataan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Din Syamsuddin (5/3/2019): “Saya menilai ada kerancuan dalam mengaitkan istilah kafir dan muwathin (warga negara) karena kedua istilah berada dalam kategori berbeda. Kafir berada dalam kategori teologis-etis, sedangkan muwathin dalam kategori sosial-politik.” Ustadz Ade yang dari tadi diam turut berkomentar, “Aneh. Istilah kafir itu sangat erat dengan akidah Islam. Adapun negara-bangsa ini landasannya bukan akidah Islam. Jadi, ada kekacauan berpikir. Ada upaya menyesuaikan ajaran Islam dengan ajaran manusia.” Ada lagi alasan bahwa Rasulullah saw. tidak menggunakan kata kafir setelah di Madinah. Sontak saja, KH Luthfi Bashori merespon, “Wong, di dalam Piagam Madinah disebut istilah kafir oleh Rasulullah.” Beliau lalu mengutip Pasal 14 Watsiqah/Piagam Madinah yang berbunyi: “Seorang Mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.” Pengurus MUI Pusat, Ustadz Teungku Zulkainain, merespon pandangan Said Aqil dengan menulis cuitan: “Nuwun Sewu Kang Said…Ayat 72 dan 73 Surat al-Maidah turunnya di Madinah, Kang. Menurut Tafsir Ibnu Katsir begitu, kan? Kalau Allah menyebut kata “kafir”, rasanya mustahil Nabi melawan Allah dengan tidak menyebutkannya. Bukankah Nabi wajib tablig? Mustahil Nabi pencitraan. Punten.” Belum lagi, setiap hukum dan istilah yang diturunkan oleh Allah SWT tetap berlaku hingga Hari Kiamat tanpa melihat apakah ayat itu diturunkan di Makkah ataukah di Madinah. Saya sampaikan, “Surat al-Kafirun turun di Makkah, tentu surat ini tetap berlaku di Madinah, bahkan berlaku hingga kapan pun.” Persoalannya, mengapa yang dipermasalahkan hanya istilah ‘kafir’. Padahal tidak ada satu pun kata ‘kafir’ dalam perundang-undangan yang berlaku. “Agama lain kan punya juga istilah untuk orang di luar agamanya,” ujar Pak Dede. “Dalam ajaran Budha, Non Budhis disebut Abrahmacariyavasa. Dalam ajaran Yahudi, orang di luar agama mereka disebut Ghoyim yang artinya lebih rendah dari binatang. Menurut ajaran Kristen, Non-Kristiani disebut domba yang tersesat. Dalam ajaran Islam, Non-Muslim disebut Kafir,” jelasnya. Ia segera menambahkan, “Begitu menurut Habib Rizieq.” Bila alasannya menyakiti perasaan atau ada kekerasan teologis, bukankah sebutan-sebutan seperti ghayim dan ‘domba tersesat’ pun menyakiti perasaan dan mengandung kekerasan teologis? Bukankah tudingan Wahabi, radikal, garis keras, fundamentalis, ekstremis dan tudingan senada juga sangat menyakitkan dan kekerasan teologis? Apalagi, kata Zakir Naik, “Jika seorang non-Muslim merasa terhina bila disebut kafir, itu karena ia belum paham dengan Islam. Dia harus mencari sumber yang tepat untuk memahami Islam dan terminologi Islam. Dengan memahaminya, ia bukan saja tidak akan merasa terhina, tetapi justru menghargai Islam dalam perspektif yang lebih tepat.” Lalu mengapa istilah kafir hendak dilenyapkan? “Pasti ada sesuatu di balik ini,” tambah Pak Dede semangat. Rupanya dengan mengeliminasi istilah kafir akan banyak hukum Islam yang dibuang. Ustadz Shiddiq al-Jawi menyampaikan dengan dieliminasinya istilah kafir maka banyak hukum Islam akan disingkirkan, antara lain keharaman seorang kafir menikahi Muslimah, keharaman menjadikan kafir sebagai pemimpin, putusnya pewarisan ahli waris Muslim dengan kafir, keharaman menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum Muslim, semua kata kafir di dalam al-Quran akan diamandemen, hukum terkait wali nikah akan berubah, dan sebagainya. Waspada, penghilangan istilah kafir adalah gerbang penghapusan hukum-hukum Islam. [Muhammad Rahmat Kurnia] |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Periklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 berikutyang Inc.